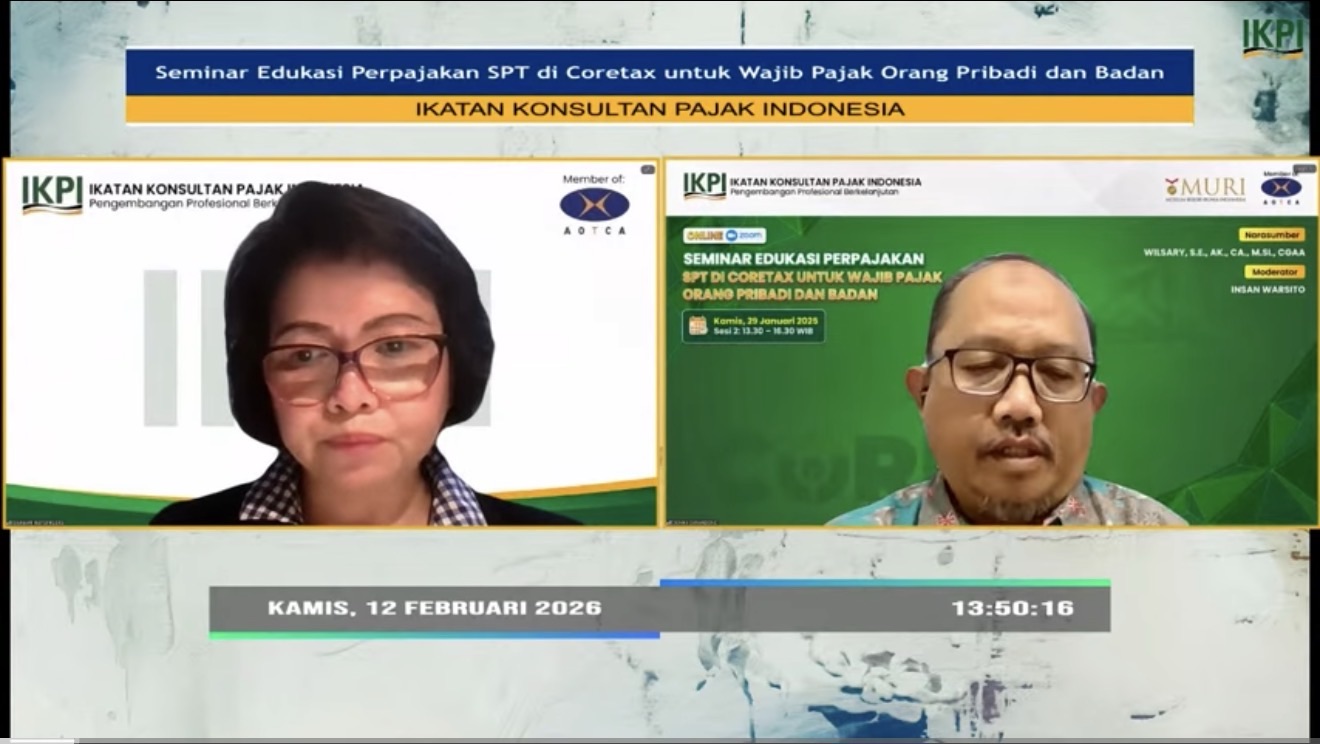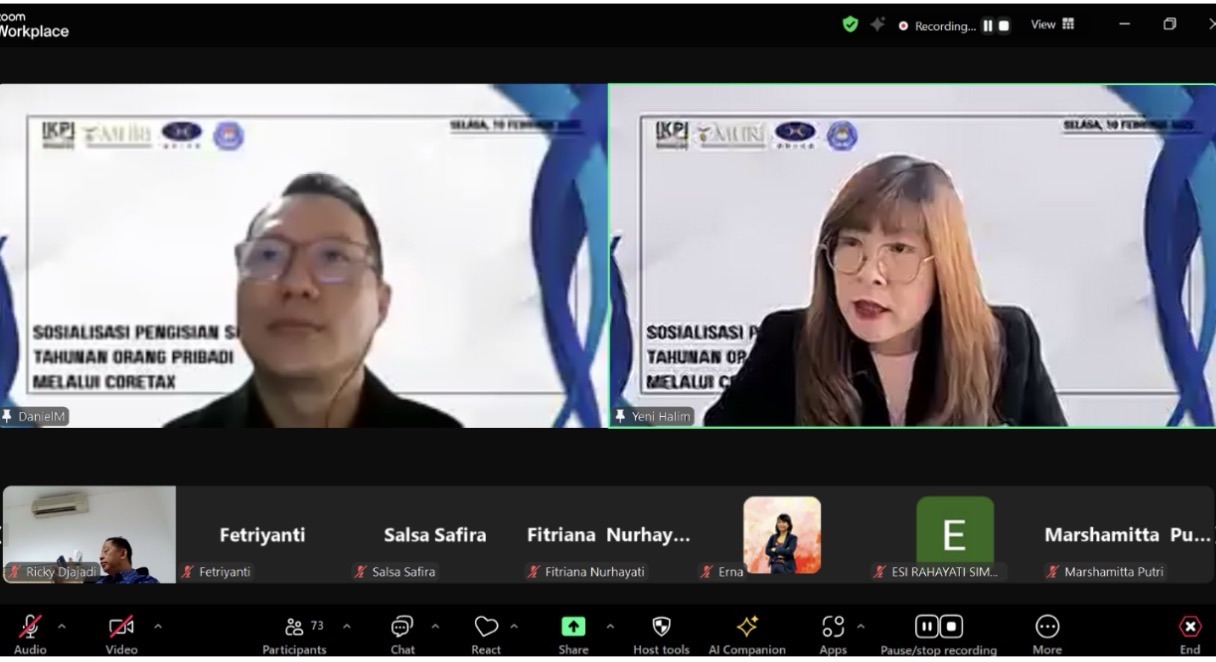IKPI, Jakarta: Bimo Wijayanto menegaskan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya kembali untuk kepentingan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Kick Off Kampanye Simpatik Ngabuburit Spectaxcular 2026 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat (13/2/2026).
Dalam sambutannya, Bimo mengajak para Relawan Pajak Renjani dan peserta yang hadir melihat pajak dari perspektif yang lebih sederhana dan membumi. Menurutnya, tanpa disadari, masyarakat telah merasakan manfaat pajak sejak memulai aktivitas harian.
Ia mencontohkan subsidi bahan bakar minyak, pembangunan dan perawatan jalan, fasilitas transportasi, hingga keberadaan aparat negara yang menjaga ketertiban umum. Seluruh layanan publik tersebut, kata dia, dibiayai oleh penerimaan pajak.
“Ketika kita menikmati jalan yang layak, subsidi energi, atau layanan publik lainnya, itu semua bersumber dari pajak,” ujarnya.
Bimo juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan dasar, pembangunan sekolah, hingga berbagai program beasiswa nasional yang memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda.
Ia mengingatkan bahwa pada era 1990-an, akses terhadap beasiswa dan pendanaan pendidikan belum sebesar saat ini. Kini, penguatan anggaran pendidikan menjadi bukti konkret bahwa pajak berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Selain sektor pendidikan, penerimaan pajak juga menopang pembiayaan kesehatan, subsidi sosial, serta berbagai program perlindungan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pelaporan dan pembayaran pajak bukan hanya kewajiban administratif, melainkan kontribusi nyata terhadap pembangunan.
Bimo menegaskan bahwa sekitar 85 persen penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan. Artinya, keberlangsungan program pembangunan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
Melalui kegiatan Spectaxcular 2026, DJP berupaya memperkuat literasi pajak, khususnya di kalangan generasi muda. Relawan pajak diharapkan mampu menyampaikan pesan bahwa pajak adalah instrumen gotong royong nasional untuk membiayai kebutuhan bersama.
“Negara ini berjalan karena pajak. Dan setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali untuk rakyat,” pungkasnya. (alf)