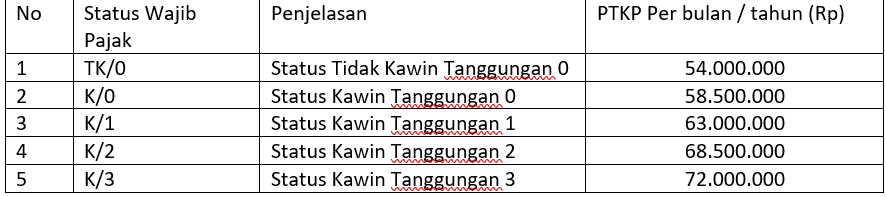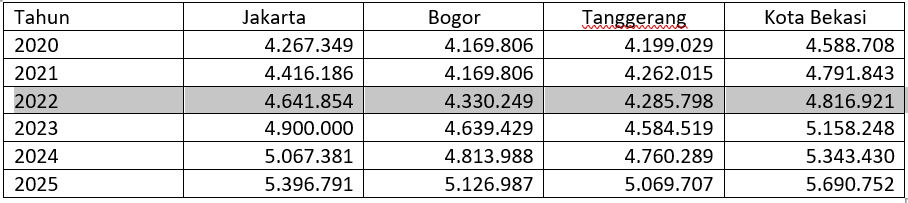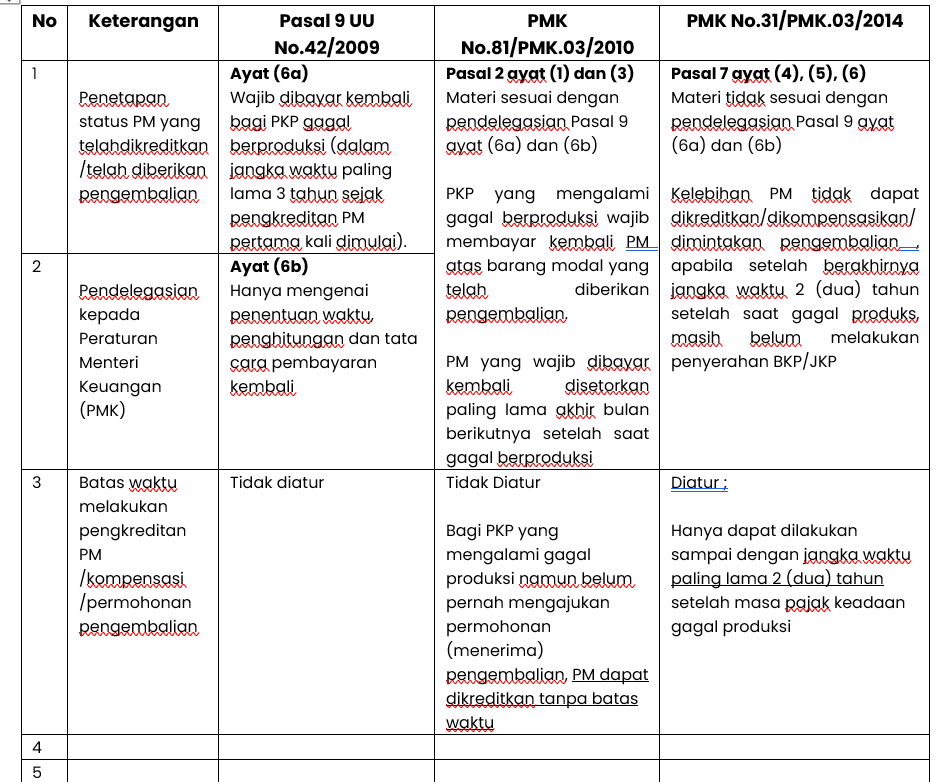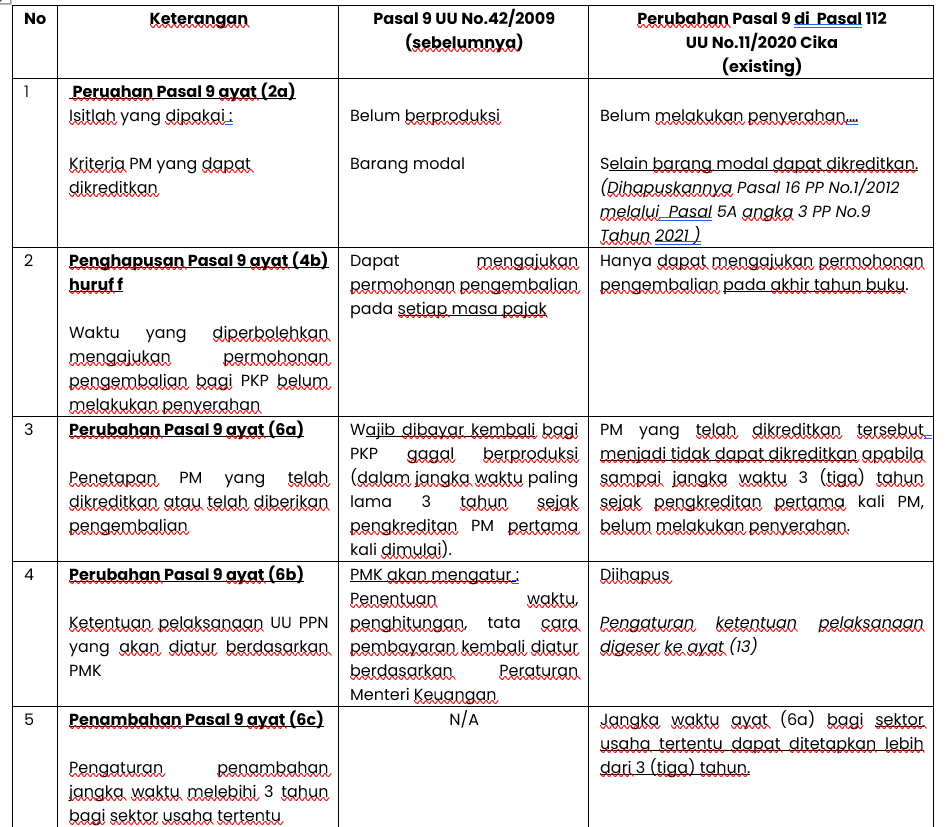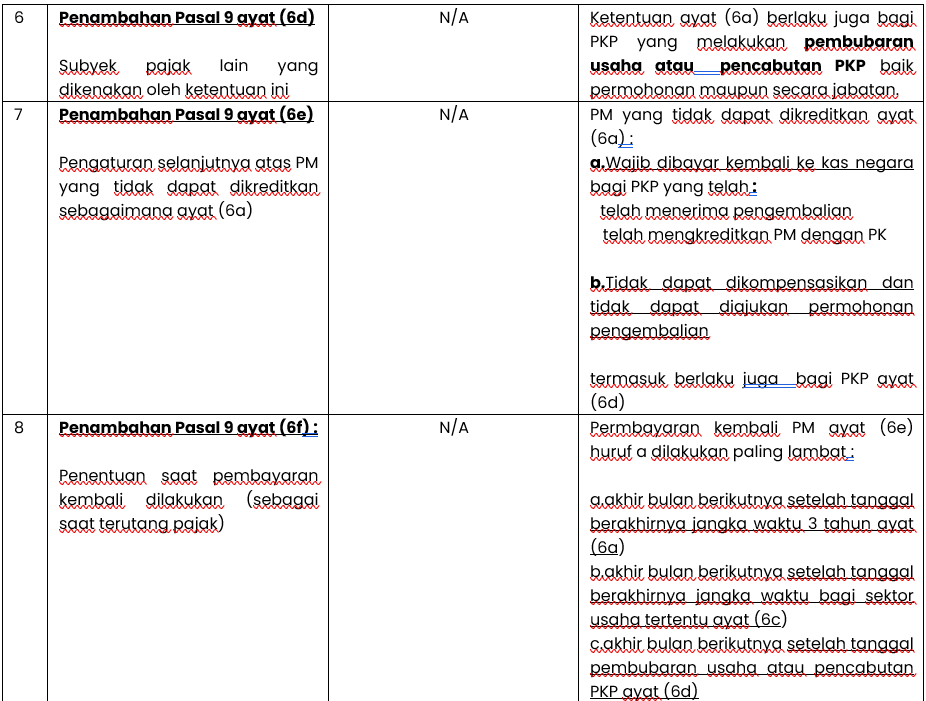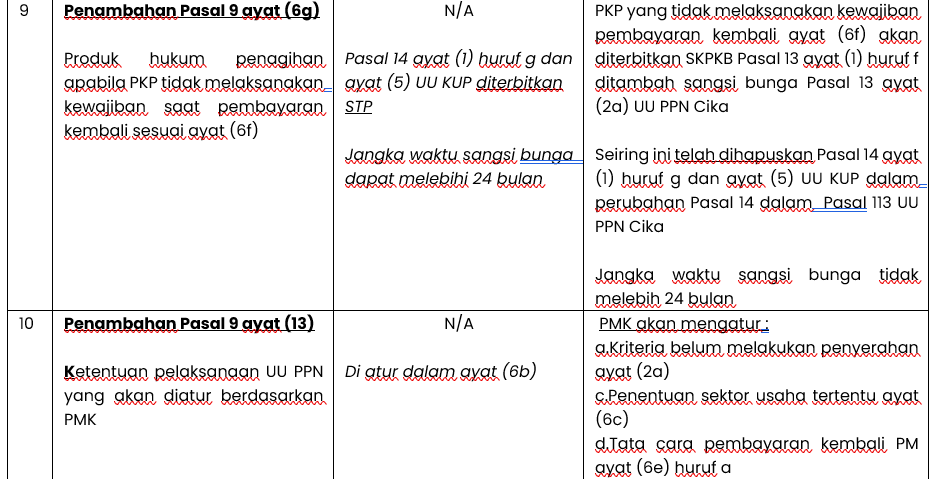Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun merupakan kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk menstimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Pemanfaatan insentif PPN DTP ini, terkait erat dengan makna kata “penyerahan” dan kata “pemindahtanganan” yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK 13/2025). Bagaimana memaknai kata “penyerahan” dan kata “pemindahtanganan” yang tercantum dalam PMK 13/2025 tersebut ..?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, tidak cukup hanya sebatas mengartikan kedua kata tersebut secara tekstual. Pemahaman konteks atas penggunaan kata “penyerahan” dan kata “pemindahtanganan” dalam PMK 13/2025 lebih memperjelas serta mempertegas makna dan tujuan digunakannya 2 (dua) kata tersebut. Walaupun sekilas secara tekstual tampak memiliki makna yang sama, namun kedua kata tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda.
Pemahaman kontekstual terhadap kata “penyerahan” dalam PMK 13/2025, setidaknya memunculkan 2 (dua) makna. Makna kata “penyerahan” yang pertama adalah penyerahan dalam arti yuridis (Penyerahan Yuridis). Penyerahan Yuridis yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a dan huruf b PMK 13/2025 dapat dilaksanakan melalui salah satu cara berikut:
• Penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah; atau
• Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas dihadapan Notaris.
Makna Penyerahan Yuridis di atas adalah penyerahan hak kepemilikan atas Barang Kena Pajak berupa rumah tapak atau satuan rumah susun dari Pengusaha Kena Pajak Penjual kepada Pembeli.
Makna kata “penyerahan” yang kedua adalah penyerahan dalam arti penguasaan fisik (Penyerahan Penguasaan Fisik). Penyerahan Penguasaan Fisik ini dalam Pasal 3 PMK 13/2025 dilaksanakan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima. Makna Penyerahan Penguasaan Fisik ini adalah penyerahan hak penguasaan fisik atau hak penggunaan atas Barang Kena Pajak berupa rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap huni secara nyata dari Pengusaha Kena Pajak Penjual kepada Pembeli.
Dengan demikian, terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima, fisik rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap huni sudah beralih penguasaan atau penggunaannya dari Pengusaha Kena Pajak Penjual kepada pembeli. Kedua makna yang terkandung dalam kata “penyerahan” tersebut merupakan syarat kumulatif yang wajib dipenuhi untuk dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP, disamping persyaratan lainnya yang tercantum dalam PMK 13/2025. Kedua makna penyerahan tersebut merupakan perbuatan menyerahkan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual kepada Pembeli.
Lebih lanjut, kedua makna kata “penyerahan” tersebut merupakan perincian/penjabaran dari pengertian penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian, khususnya perjanjian jual beli dan jual beli dengan angsuran yang tercantum dalam Pasal 1A ayat 1 huruf a Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (“UU PPN”).
Sama halnya dengan cara memahami konteks kata “penyerahan” di atas, kata “pemindahtanganan” dalam PMK 13/2025 tidak dapat dipahami sebatas hanya secara tekstual. Bahkan kata “pemindahtanganan” dalam PMK 13/2025 tidak dapat diartikan terpisah dari kata “penyerahan”. Terdapat 3 (tiga) makna kata “pemindahtanganan” dalam PMK 13/2025. Makna kata “pemindahtangan” yang pertama adalah penyerahan pertama kali rumah tapak atau satuan rumah susun baru siap huni oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menyelenggarakan pembangunan kepada pembeli. Makna kata “pemindahtanganan” yang pertama ini, dapat ditemui dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b juncto Pasal 4 ayat 2 huruf b PMK 13/2025.
Makna yang pertama ini penting sekali dipahami guna membedakan pemindahtanganan rumah tapak atau satuan rumah susun siap huni yang bukan baru atau pernah dipindahtangankan (atau yang sering disebut dengan rumah tapak atau satuan rumah susun second hand).
Makna kata “pemindahtanganan” yang kedua adalah pemindahtanganan yang merupakan kelanjutan dari pemindahtanganan yang pertama, pemindahtanganan ini dilakukan oleh pihak yang semula merupakan pembeli rumah tapak atau satuan rumah susun baru kepada pihak lain/pembeli selanjutnya.
Pemindahtanganan ini dilakukan dalam rentan waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual kepada Pembeli. Makna kata “pemindahtanganan” yang kedua ini dapat ditemui dalam Pasal 9 ayat 1 huruf e juncto Pasal 10 huruf g PMK 13/2025. Pemindahtanganan dalam makna yang kedua ini akan mengakibatkan insentif PPN DTP yang telah diterima menjadi terutang dan dapat ditagih oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Makna kata “pemindahtanganan” yang ketiga adalah pemindahtanganan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual atas rumah tapak atau satuan rumah susun second hand kepada pembeli.
Benang merah dari makna kata “pemindahtanganan” yang ketiga ini adalah rumah tapak atau satuan rumah susun yang sebelumnya pernah dipindahtangankan (bukan baru / second hand). Kata “pemindahtanganan” dalam makna yang ketiga dan kedua di atas adalah pemindahtanganan rumah tapak atau satuan rumah susun yang tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP.
Demikian makna – makna dari kata “penyerahan” dan kata “pemindahtanganan” yang secara kontekstual penulis temukan dalam PMK 13/2025. Semoga tulisan yang jauh dari sempurna dan singkat ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan Konsultan Pajak seprofesi, khususnya bagi rekan-rekan Konsultan Pajak yang memiliki klien perusahaan real estat atau klien yang bermaksud memanfaatkan fasilitas PPN DTP.
Penulis adalah anggota IKPI Cabang Bandung
Hari Yanto
Email: hari_yanto_sh@yahoo.co.id
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis