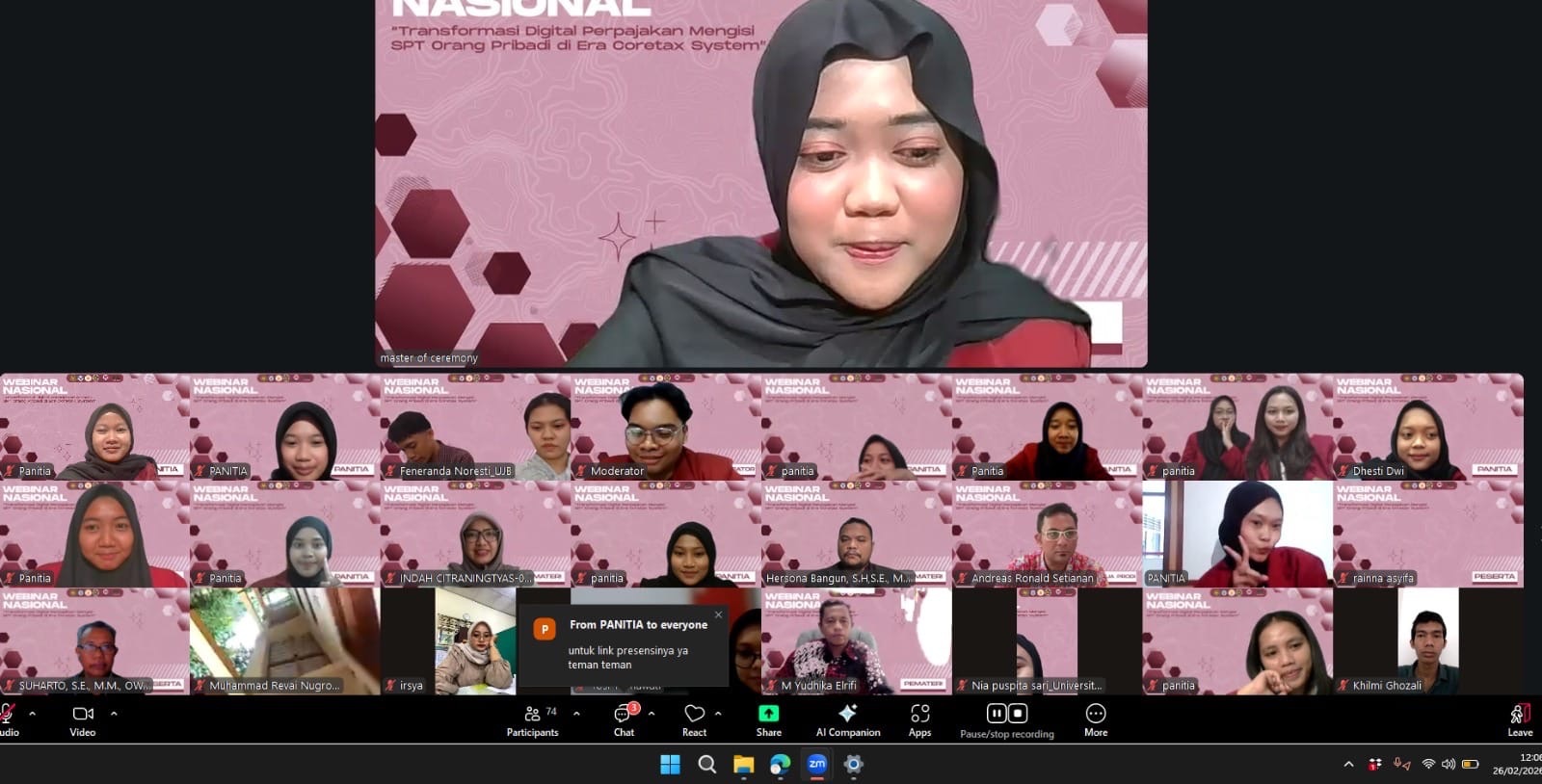IKPI, Bitung: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bitung membuka Klinik Pajak Gratis di Paris Superstore, Kota Kotamobagu, pada Rabu–Kamis, 25–26 Februari 2026. Kegiatan ini digelar sebagai respons atas meningkatnya antrean wajib pajak di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan.
Ketua IKPI Cabang Bitung, Dr. Denny F. Makisanti mengatakan banyak wajib pajak yang datang ke KPP karena belum memahami mekanisme pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi Coretax.
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan. Banyak wajib pajak belum familiar dengan pelaporan melalui Coretax. Karena itu, IKPI Cabang Bitung terpanggil untuk ikut membantu melakukan sosialisasi dan pendampingan,” ujar Denny.
Menurutnya, Klinik Pajak atau Pojok Pajak ini sengaja ditempatkan di lokasi strategis dan ramai, yakni Paris Superstore, agar lebih mudah dijangkau masyarakat tanpa harus datang ke kantor pajak.
Selama dua hari pelaksanaan, antusiasme warga Kotamobagu dan sekitarnya terlihat tinggi. Wajib pajak datang untuk berkonsultasi sekaligus meminta pendampingan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax.
Pengurus dan anggota IKPI Cabang Bitung secara sigap melayani setiap wajib pajak yang hadir. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan pendekatan edukatif, sehingga wajib pajak tidak hanya selesai melapor, tetapi juga memahami prosesnya.
Denny menegaskan bahwa layanan ini diberikan secara gratis sebagai bentuk kontribusi nyata organisasi profesi kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar membantu pelaporan, tetapi bagian dari edukasi. Kami ingin wajib pajak semakin paham dan mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara konsultan pajak dan otoritas pajak menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan yang lebih baik. Dengan meningkatnya literasi perpajakan, diharapkan kepatuhan sukarela wajib pajak juga semakin meningkat.
Melalui Klinik Pajak Gratis ini, IKPI Cabang Bitung menunjukkan peran aktifnya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan sekaligus meningkatkan kesadaran pajak di tengah masyarakat. (bl)