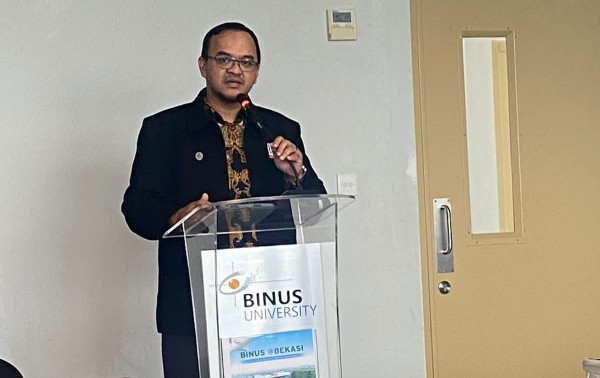IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menerapkan sistem keamanan Multi-Factor Authentication (MFA) pada aplikasi DJP Online. Hal ini guna melindungi data Wajib Pajak dan mencegah tindakan penipuan.
Kebijakan ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor PENG-33/PJ.09/2024 yang diteken oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, pada 2 Desember 2024.
Menurut Dwi, penerapan MFA bertujuan untuk memperkuat protokol keamanan data dalam rangka implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP atau Coretax). Proses transisi penerapan MFA akan berlangsung hingga 31 Desember 2024.
Dikatakannya, selama masa transisi ini, DJP mengimbau agar Wajib Pajak memperbarui data pribadi seperti nomor handphone dan alamat email pada aplikasi DJP Online, yang digunakan untuk keperluan perpajakan.
Dwi mengingatkan Wajib Pajak untuk secara berkala memperbarui kata sandi (password) aplikasi DJP Online sebagai langkah preventif terhadap potensi kebocoran data. “Kami juga menyarankan Wajib Pajak untuk memperbarui kata sandi secara berkala,” ujarnya.
Sekadar informasi, sejak penerapan MFA, pengguna yang mengakses aplikasi DJP Online diwajibkan untuk melakukan verifikasi melalui nomor token yang diterima melalui email, SMS, atau aplikasi M-Pajak. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan ekstra terhadap data pribadi Wajib Pajak.
DJP Kemenkeu juga mengingatkan agar Wajib Pajak berhati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan DJP. Ditegaskan, bahwa mereka tidak pernah meminta informasi sensitif seperti nama ibu kandung, file aplikasi (APK), atau transfer uang.
Semua komunikasi resmi DJP hanya dilakukan melalui nomor WhatsApp terverifikasi, yakni +62 822-3000-9880.
Dengan penerapan MFA ini, DJP berharap dapat lebih memastikan perlindungan terhadap data pribadi Wajib Pajak serta mencegah ancaman keamanan di dunia maya. (alf)