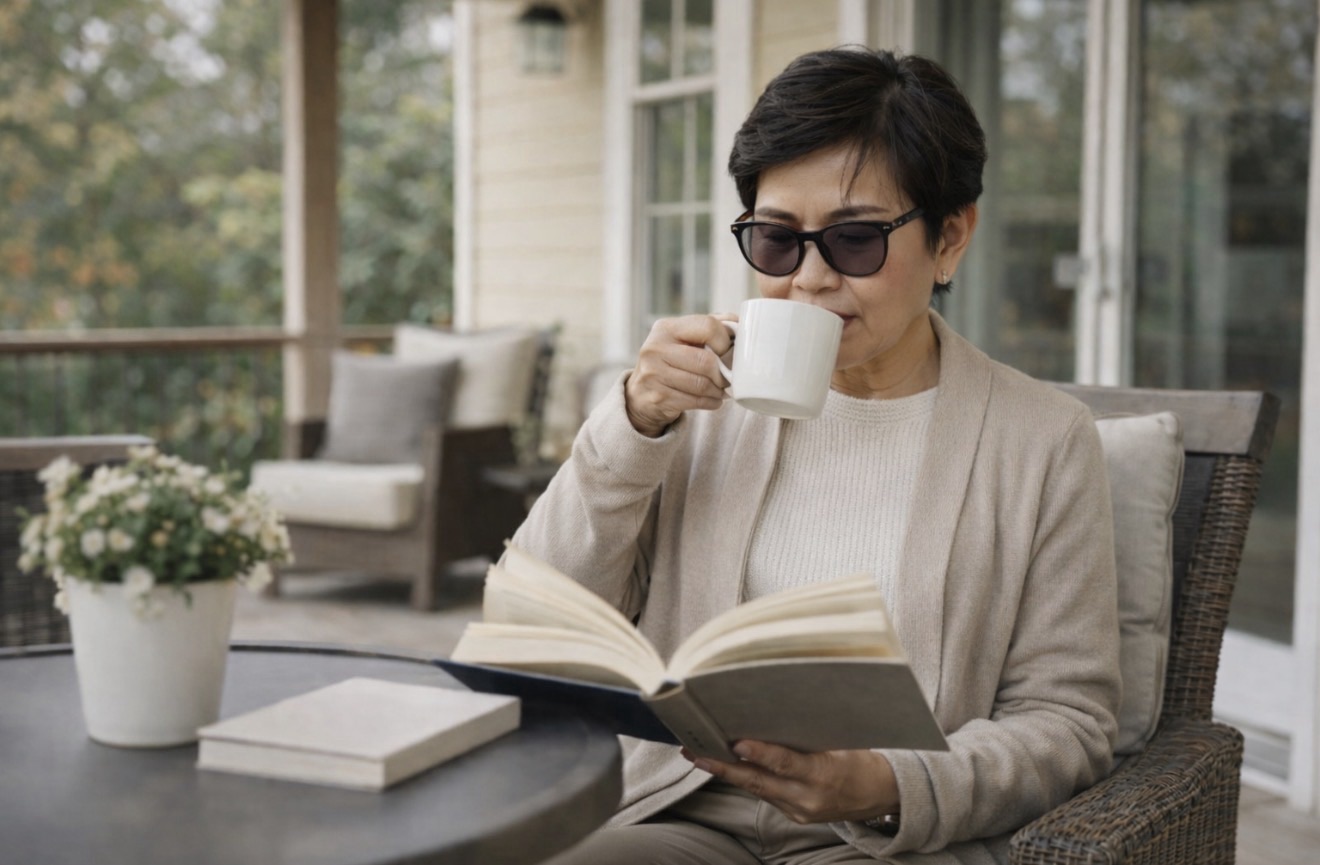Isu restitusi pajak dalam beberapa waktu terakhir mencuat sebagai salah satu topik paling hangat dalam diskursus fiskal Indonesia. Sepanjang tahun 2025, nilai restitusi melonjak tajam hingga mencapai Rp361,2 triliun, naik 35,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp265,7 triliun (Kemenkeu, 2026). Lonjakan besar ini terutama berasal dari restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri.
Angka yang begitu signifikan menimbulkan kekhawatiran karena terjadi di tengah melemahnya penerimaan pajak neto dan melebarnya shortfall penerimaan negara, sehingga menekan ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program pembangunan.
Sorotan terhadap restitusi pajak tidak hanya datang dari ranah kebijakan fiskal, tetapi juga dari pelaku usaha yang merasakan langsung dampaknya. Mekanisme yang semestinya menjadi instrumen keadilan bagi wajib pajak kini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi, efisiensi, serta pengaruhnya terhadap arus kas perusahaan.
Bagi dunia usaha, khususnya sektor ekspor dan industri besar, restitusi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan faktor penentu kelancaran operasional dan daya saing. Karena itu, pembahasan mengenai kebijakan restitusi pajak tidak bisa dianggap remeh, melainkan harus dipahami sebagai isu strategis yang menyentuh keberlangsungan bisnis sekaligus kepercayaan antara pelaku usaha dan pemerintah.
Restitusi Pajak Harapan Besar Pelaku Usaha dan Industri
Bagi pelaku usaha, terutama sektor ekspor dan industri besar, restitusi pajak bukan sekadar angka dalam laporan fiskal, melainkan instrumen vital yang menentukan kelancaran arus kas. Pengembalian kelebihan bayar pajak memberi ruang bagi perusahaan menjaga likuiditas, membiayai operasional, dan memperkuat daya saing. Ketika restitusi berjalan lancar, perusahaan dapat merencanakan investasi jangka panjang dengan percaya diri. Sebaliknya, proses yang berbelit atau tertunda langsung berdampak pada cash flow, bahkan bisa menghambat ekspansi maupun keberlangsungan usaha.
Lonjakan restitusi pada 2025 yang mencapai Rp361,2 triliun menambah ketidakpastian. Kebijakan yang berubah-ubah dan verifikasi yang belum sepenuhnya transparan membuat pelaku usaha ragu apakah hak mereka akan dikembalikan tepat waktu. Ketidakpastian ini mengganggu perencanaan bisnis jangka panjang, memaksa perusahaan menyiapkan skenario cadangan untuk menghadapi kemungkinan restitusi tertunda. Karena itu, implementasi restitusi pajak yang baik dan konsisten menjadi harapan besar dunia usaha: bukan hanya untuk menjaga kelancaran arus kas, tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang stabil, transparan, dan berkeadilan.
Melihat dampak tersebut, pelaku usaha menaruh harapan besar agar mekanisme restitusi dijalankan lebih baik. Restitusi yang cepat, transparan, dan konsisten adalah kunci menjaga likuiditas sekaligus memastikan keberlangsungan operasional. Dunia usaha berharap pemerintah menghadirkan sistem sederhana dan efisien, sehingga hak pengembalian pajak diterima tepat waktu tanpa proses panjang yang menguras energi maupun biaya tambahan. Harapan ini bukan sekadar kepastian finansial, tetapi juga tentang membangun rasa percaya bahwa negara hadir sebagai mitra pertumbuhan bisnis.
Namun, kritik terhadap kebijakan restitusi tetap mengemuka. Banyak pelaku usaha menilai prosedur masih berbelit, membuka ruang suap, dan menimbulkan ketidakpastian yang merugikan. Ketika restitusi menjadi arena korupsi, kepercayaan terhadap birokrasi pajak pun terkikis.
Tantangan: Transparansi dan Pengawasan Demi Menjaga Kepercayaan Publik
Restitusi pajak yang seharusnya menjadi jembatan hubungan baik antara pemerintah dan pelaku usaha kini memaksa Kementerian Keuangan meninjau ulang aturan serta mempercepat reformasi sistem perpajakan. Tantangan terbesar dalam kebijakan ini adalah potensi penyalahgunaan mekanisme yang semestinya menjamin keadilan bagi wajib pajak. Karena itu, pekerjaan rumah utama pemerintah adalah menciptakan sistem yang transparan dengan pengawasan yang kuat.
Kasus OTT KPK di Banjarmasin pada Februari 2026 menjadi bukti nyata bahwa restitusi dapat dijadikan ladang korupsi. Dalam kasus tersebut, pejabat pajak diduga menerima suap Rp1,5 miliar untuk memperlancar restitusi PPN senilai Rp48,3 miliar (Media Indonesia, 2026). Fakta ini menunjukkan bahwa proses verifikasi masih membuka ruang praktik “uang pelicin,” merusak integritas sistem perpajakan yang sedang dibangun.
Selain itu, KPK menegaskan bahwa restitusi kerap dijadikan komoditas suap, di mana pejabat pajak dan pihak swasta melakukan transaksi ilegal untuk mempercepat pengembalian. Modus yang muncul berupa “uang apresiasi” agar permohonan diterima tanpa hambatan, terutama di sektor dengan restitusi besar seperti perkebunan dan ekspor. Kekhawatiran semakin kuat karena adanya pejabat pajak yang merangkap jabatan di banyak perusahaan, menimbulkan konflik kepentingan dan memperbesar risiko penyalahgunaan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa integritas sistem perpajakan masih menghadapi ujian berat. Dampaknya bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghantam kepercayaan pelaku usaha terhadap birokrasi pajak. Dunia usaha yang seharusnya mendapat kepastian justru dihadapkan pada risiko ketidakadilan dan biaya tambahan akibat praktik korupsi. Ketidakpercayaan ini berpotensi mengganggu iklim investasi, karena pelaku usaha ragu apakah hak mereka benar-benar dijamin tanpa jalur tidak resmi.
Dengan demikian, celah korupsi dalam restitusi pajak bukan sekadar kasus insidental, melainkan masalah sistemik yang harus segera ditangani. Memperkuat integritas sistem restitusi pajak menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Kementerian Keuangan agar mekanisme berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi yang merusak kepercayaan publik dan iklim usaha di Indonesia tumbuh sehat dan berkeadilan.
Banyak Pekerjaan Rumah Pemerintah Agar Restitusi Pajak Memenuhi Harapan Pelaku Usaha
Untuk memastikan restitusi pajak benar-benar berpihak pada pelaku usaha dan tidak menjadi sumber ketidakpastian maupun praktik negatif, pemerintah perlu menjalankan reformasi menyeluruh. Penyederhanaan prosedur menjadi langkah mendesak, proses yang panjang dan berbelit harus dipangkas melalui digitalisasi penuh, sehingga pengajuan dan verifikasi berlangsung cepat, transparan, dan minim interaksi tatap muka yang rawan suap. Selanjutnya, penguatan pengawasan berbasis teknologi dengan data analitik dan audit otomatis akan membantu mendeteksi anomali sejak dini dan menekan potensi penyalahgunaan.
Pemerintah juga perlu menetapkan kepastian waktu pencairan restitusi dengan standar layanan yang jelas, agar pelaku usaha dapat merencanakan arus kas tanpa harus menyiapkan skenario cadangan akibat keterlambatan. Transparansi harus ditingkatkan melalui publikasi laporan restitusi berkala, sehingga konsistensi kebijakan dapat dinilai secara terbuka. Di sisi lain, penegakan hukum tegas terhadap oknum pajak maupun pihak swasta yang terlibat praktik suap akan menjadi sinyal kuat bahwa integritas sistem dijaga.
Pada konteks ini, patut diapresiasi langkah Kementerian Keuangan menghadirkan Core Tax Administration System (Coretax), sebuah sistem inti administrasi perpajakan terintegrasi yang menggantikan 19 sistem lama menjadi satu platform digital dengan berbagai fitur unggulan. Coretax diharapkan mampu menyederhanakan proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat pengawasan. Meski demikian, sistem ini masih belum sempurna dan perlu terus disempurnakan agar benar-benar efektif serta berpihak pada pelaku usaha.
Isu restitusi pajak jelas bukan sekadar persoalan teknis fiskal, melainkan menyangkut kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha. Lonjakan restitusi beberapa waktu lalu, ditambah kasus-kasus korupsi yang mencuat, memperlihatkan bahwa sistem yang ada masih menyimpan banyak celah. Bagi dunia usaha, restitusi adalah instrumen vital untuk menjaga arus kas dan keberlangsungan operasional, sehingga ketidakpastian atau praktik negatif dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak serius terhadap iklim bisnis dan investasi.
Karena itu, reformasi sistem restitusi pajak harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu menghadirkan mekanisme yang sederhana, transparan, dan konsisten, sekaligus memperkuat pengawasan serta penegakan hukum agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan. Dengan dukungan sistem digital seperti Coretax yang terus diperbaiki, restitusi pajak dapat kembali pada tujuan awalnya: menjadi instrumen keadilan fiskal yang mendukung pertumbuhan usaha, memperkuat daya saing, dan membangun kepercayaan pelaku bisnis terhadap negara. Pada akhirnya, keberhasilan reformasi ini akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.
Penulis adalah Anggota IKPI Cabang Bogor dan Pemerhati Kebijakan Fiskal
Hotman Auditua S,S.E.,M.E.M.Si.,BKP
Email: hotman.auditua@gmail.com
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis