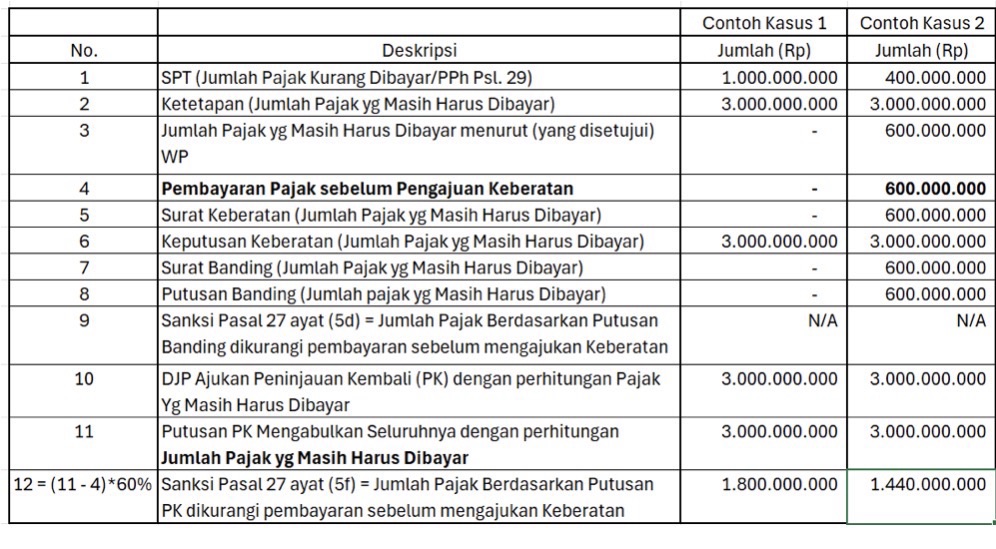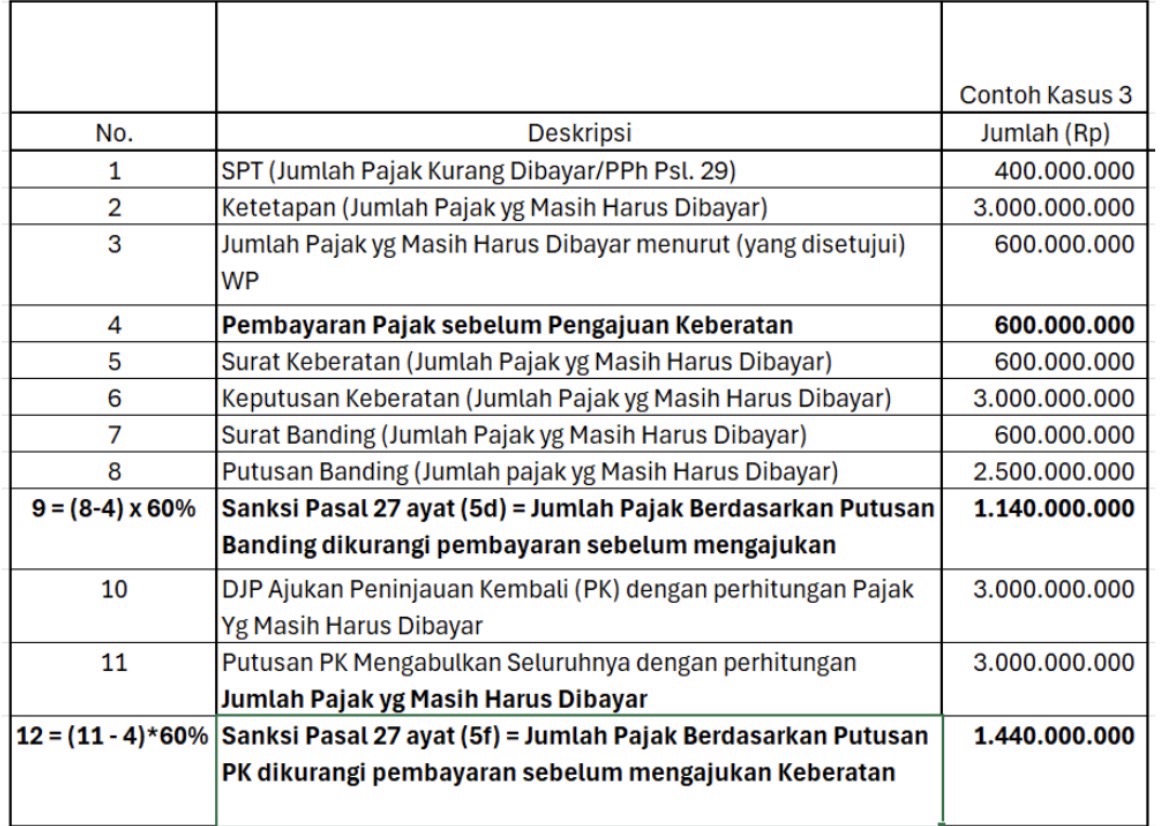ABSTRACT
This research aimed to find out the Fraud Pentagon on the indication of fraud for financial statements The factors of fraud pentagon consist of five indicators, i.e. (1) Opportunity was proxy with Nature of Industry dan Ineffective Monitoring, (2) Capability was proxy with change in director, (3) Rationalization was proxy with Change in Auditor, (4) Arrogance was proxy with Political Connection, and (5) Pressure was proxy with Financial Target and Financial Stability. There were seven independent variables used in the hypothesis that affected the fraud of financial statements and the dependent variable of fraud (F-score) to find out the financial statement fraud. Furthermore, this research used a quantitative approach with a sample consisting of 72 agricultural companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the observation periods of 2016-2019 with the purposive sampling method and the multiple linear analysis used software SPSS 24 version. Moreover, the research result showed that the Financial Target and Financial Stability variables affected the fraud of financial statements. Meanwhile, the variables of Nature of Industry, Ineffective Monitoring, Change in Director, Change in Auditor, and Political Connection did not affect the fraud of financial statements.
Keywords: fraud of financial statements, pentagon fraud, f score
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Fraud Pentagon terhadap indikasi adanya kecurangan laporan keuangan. Faktor-faktor dalam fraud pentagon terdiri dari lima indikator diantaranya meliputi (1) Opportunity diproksikan dengan Nature of Industry dan Ineffective Monitoring, (2) Capability diproksikan dengan change in director, (3) Rationalization diproksikan dengan change in auditor, (4) Arrogance diproksikan dengan political connection, dan (5) Preasure diproksikan dengan financial target dan financial stability. Terdapat 7 (tujuh) variabel independen yang dihipotesiskan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dan variabel dependen kecurangan (F-score) digunakan untuk mengetahui adanya kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel terdiri dari 72 perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan 2016-2019 dengan motode purposive sampling dan analisis linier berganda menggunakan software SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel financial target dan financial stability memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan pada variabel Nature of Industry, Ineffective Monitoring, change in director, change in auditor, dan political connection tidak menunjukan adanya pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
Kata Kunci: kecurangan laporan keuangan, fraud pentagon, f-score
PENDAHULUAN
Perusahaan yang berstatus go public memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan, publik dapat menilai kondisi perusahaan yang dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan berinvestasi, untuk itu perusahaan harus mampu menghadapi berbagai risiko dan sebisa mungkin memiliki berbagai strategi bisnis salah satunya adalah pemasalahan fraud. Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai lembaga profesional salah satunya dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan. Keadaan perusahaan memiliki pengaruh signifikan bagi kondisi keuangan perusahaan. Efisiensi dan efektifitas kinerja perusahaan dapat menjadi sebuah tolok ukur dalam laporan keuangan (Aprilia, 2017). Menurut Maria dan Gerianta (2015), tindakan kecurangan pada laporan keuangan berpotensi adanya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tidak relevan dan menyebabkan salah saji material sehingga menyesatkan stake holder.
Berdasarkan hasil survei Association Certified Fraud of Examiners (ACFE) pada tahun 2016 menyatakan, bahwa ditahun 2016 perusahaan di Indonesia menduduki peringkat kedua se-Asia Pasifik dalam Tindakan kecurangan laporan keuangan. CPI (Corruption Perception Index) juga memiliki data tentang peringkat Indonesia, yang mana perusahaannya melakukan korupsi, seperti pelaporan keuangan ke publik yang tidak transparan. Menurut CPI (Corruption Perception Index) Indonesia menduduki peringkat ke 90 dari 176 negara dalam melakukan korupsi (Transparansi International, 2016). Hal ini berarti bahwa masih terdapat 51% persen perusahaan-perusahaan di Indonesia semua sektor melakukan kecurangan laporan keuangan. Tindakan kecurangan laporan keuangan yang terjadi dibeberapa sektor industri di perusahaan-perusahaan Indonesia sudah banyak dilakukan. Data lain dari survey fraud di Indonesia yang dilakukan oleh ACFE Indonesia (2016) bahwa fraud yang berkaitan dengan laporan keuangan menduduki peringkat ketiga.
Skandal kecurangan pada laporan keuangan di Indonesia seperti yang terjadi pada PT. Hanson Internasional pada 2016 silam …
Skandal kecurangan pada laporan keuangan di Indonesia seperti yang terjadi pada PT. Hanson Internasional pada 2016 silam dimana PT. Hanson diketahui tidak menyajikan informasi perjanjian pengikatan jual beli kavling siap bangun di perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 mengenai penjualan Kasiba yang kemudian berujung denda senilai Rp5.000.000.000 dengan pelanggaran yang dilakukan yaitu terkait Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44). Kasus kecurangan lainya di Indonesia pernah dilakukan oleh PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang sektor agrikultur. Pada laporan keuangan tahun 2017 UNSP menunjukan defisiensi modal dengan total liabilitas jangka pendek konsolidasian melampaui total aset lancar konsolidasiannya. Pada saat yang bersamaan muncul persoalan beban utang UNSP yang terkait fasilitas pinjaman sebesar US$250.000.000 dari 11 lembaga keuangan yang difasilitasi oleh Credit Suisse AG.
Peneliti menggunakan sektor agrikultur sebagai studi kasus penelitian dimana sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini akan menerapkan Fraud pentagon theory untuk menganalisis indikasi kecurangan laporan keuangan, maka adapun permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah nature of Industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?, (2) Apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?, (3) Apakah change in director berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?, (4) Apakah change in auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?, (5) Apakah political connection berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?, (6) Apakah financial traget berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?, (7) Apakah financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
TINJAUAN TEORITIS
Teori Keagenan (Agency Theory)
Agency theory merupakan salah satu bentuk asumsi yang menyatakan konflik yang terjadi dari suatu akibat adanya benturan kepentingan baik dari pihak agen maupun prinsipal di dalam suatu perusahaan yang beroperasi (Jensen dan Meckling, 1976). Bagi pelaku bisnis dalam sebuah entitas yang terstruktur memiliki tanggung jawab penuh terhadap jalannya fungsi perusahaan yang diberi tugas masing-masing sesuai bidang dan manajer yang juga bertanggung jawab untuk mengoptimalkan supaya perusahaan tetap berjalan dengan tujuan awal perusahaan serta dapat memuaskan kepentingan pemilik (principal), disisi lain manajer juga memiliki kepentingan pribadi dalam upaya mensejahterahkan anggota pelaku perusahaan.
Berdasarkan hal tersebut diatas secara tidak langsung para pelaku perusahaan di tuntut supaya dapat memperoleh penghasilan dan laba yang tinggi dikarenakan jika laba tinggi dapat memberikan nilai tambah terhadap perusahaan, sehingga investor banyak yang tertarik untuk investasi di perusahaan tersebut. Perusahaan mengemukakan bahwa perusahaan berusaha untuk mempertahankan dividen (Lintner, 1956). Namun disisi lain pihak dari agen memiliki tujuan yang menjadi target tersendiri demi mencapai bonus yang akan diterima. Prinsipal yang menghendaki laba yang tinggi atas investasinya, dengan agen yang mengupayakan agar mendapatkan bonus yang besar sebagai wujud apresiasi atas hasil kerjanya (Martantya, 3).
Fraud Model
Fraud model terus mengalami perubahan dan bentuk perkembangan yang sedemikian rupa, fraud model pertama kali di perkenalkan oleh Donald R. Cressey (1953) yang kemudian lebih dikenal dengan istilah fraud triangle. Dalam teori segitiga kecurangan yang dicetuskan oleh D.R. Cressey, mengkategorikan tiga kondisi selalu ada dalam kecurangan perusahaan, yaitu Tekanan (pressure/incentive), Peluang (opportunity), Rasionalisasi (rationalization). Seiring berkembangnya waktu komponen fraud pendagon pun dapat dilihat dari ISA No. 240 yang dapat dikategorikan diantaranya seperti Peluang (Oppurtunity) yaitu, Nature of Industry dan Ineffective Monitoring. Kategori tekanan (pressure/incentive) terdiri dari Financial Targets dan financial stability. Sedangkan kategori rasionalisasi (Rationalization) adalah rationalization.
Crowe pada tahun (2010) telah menemukan bahwa elemen Arogansi (Arrogance) juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Crowe pada saat itu juga memberikan variabel baru pada fraud triangle theory dan elemen kompetensi (competence) didalamnya, sehingga teori fraud yang dikemukakan oleh Crowe menjadi bentuk penyempurnaan dari fraud triangle theory dan fraud diamod theory yang memiliki lima elemen indikator, yaitu kesempatan (opportunity), kapabilitas (capability), rasionaliasi (rationalization), arogansi (arrogance) dan tekanan (preassure), yang kemudian pengembangan tersebut dikenal sebagai fraud pentagon theory.
Kecurangan Laporan Keuangan
Kecurangan merupakan bentuk tindakan seseorang yang dengan sengaja dilakukan untuk merampas harta hak milik orang lain dengan cara penipuan, manipulasi maupun dengan segala cara lainnya yang tidak dibenarkan. Kecurangan menurut audit merupakan tindakan yang dapat dilakukan dengan mengubah maupun menghapus jumlah angka atau nominal atau dalam kata lain adalah memanipulasi informasi yang dilakukan dengan sengaja dalam penyajian laporan keuangan perusahaan sehingga dapat mengelabui para pengguna laporan keuangan. Kecurangan Laporan Keuangan merupakan suatu kelalaian maupun penyalahsajian yang disengaja dalam jumlah tertentu atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menipu para pengguna laporan keuangan (Australian Auditing Standards).
Perumusan Hipotesis
Pengaruh Nature of Industry Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Nature of industry merupakan kondisi ideal sebuah entitas dalam lingkungan industry. Kondisi Nature of industry dapat ditinjau dari posisi piutang usaha perusahaan yang dapat memicu respon manajer perusahaan yang bersifat asimetris. Perusahaan akan cenderung menekan jumlah piutang dan akan melakukan penerimaan kas yang lebih banyak, hal tersebut diterapkan agar supaya perusahaan ingin terlihat baik (Sihombing dan Rahardjo, 2014). Summers dan Sweeney (1998) dalam penelitiannya menyatakan terdapat dua akun laporan keuangan yang biasa dilakukan manipulasi oleh manajar yaitu terdiri dari akun piutang dan persediaan.
Menurut Nugraheni dan Triatmoko (2017) nature of industry memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sebaliknya dari hasil penelitian Kurnia (2017), Putriasih et al., (2016) menemukan bahwa nature of industry memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan urauian diatas, maka digunakan hipotesis:
H1: Nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
Pengaruh Ineffective Monitoring Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Potensi adanya praktik kecurangan atau Fraud merupakan salah satu dampak dari pengawasan atau monitoring yang masih kurang atau lemah sehingga memberi peluang kepada agen atau manajer untuk melakukan tindakan menyimpang dengan melakukan manajemen laba (Andayani, 2010). Praktik kecurangan atau Fraud dapat diminimalkan salah satunya dengan penerapan bentuk pengawasan yang baik. Dalam hal ini dewan komisaris independen dipercaya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan. Dewan komisaris bertugas untuk menjamin berjalannya strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.
Tiffani (2015) dalam penelitiannya menyatakan ineffective monitoring berpengaruh negative Terhadap Laporan Keuangan. Sebaliknya penelitian dari Kartika dan Triatmoko (2017) menemukan bahwa ineffective monitoring tidak berpengaruh dengan Kecurangan Laporan Keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka digunakan hipotesis:
H2: Ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
Pengaruh Change In Director Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Change in directors atau pergantian dewan direksi, dalam hal ini dianggap perlunya dilakukan pergantian dewan direksi karena perusahaan sebagai bentuk upaya memperbaiki kinerjanya agar lebih baik dengan diatur oleh dewan direksi yang lebih berkompeten dari yang sebelumnya. Dalam praktiknya pergantian direksi yang dilakukan tersebut dapat juga dikarenakan adanya kepentingan politik tertentu (Tessa dan Harto, 2016). Berdasarkan hal tersebut, terdapat indikasi bahwa perusahaan berupaya untuk menghilangkan jejak kecurangan atau fraud trail yang mungkin telah dilakukan sehingga adanya pertimbangan terhadap pergantian direksi.
Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Saputra dan Kusumaningrum (2017). Dalam penelitiannya Triyanto (2020) menemukan bahwa change in directors berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Tessa dan Harto (2016) menyatakan bahwa change in directors tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Berdasarkan uraian diatas, maka digunakan hipotesis:
H3: Change in directors berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
Pengaruh Change In Auditor Terhadap kecurangan Laporan Keuangan
Change in Auditor dapat diteliti dengan menggunakan skala atau jumlah dari pergantian auditor yang digunakan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah auditor eksternal perusahaan, dengan asumsi apabila perusahaan telah melakukan pergantian auditor dimana juga auditor pihak independen yang menguasai perusahaan tersebut maka terdapat potensi terhadap auditor tersebut menolak untuk memeriksa perusahaan dikarenakan berisiko tinggi untuk diperiksa dan hal tersebut secara langsung juga berpotensi menimbulkan kecurangan dalam perusahaan.
Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Andri (2014) yang menyatakan change in auditor berpengaruh positif Terhadap Laporan Keuangan. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Tiffani (2015) yang menyatakan change in auditor tidak berpengaruh Terhadap Laporan Keuangan. Maka berdasarkan deskripsi diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
H4: Change in auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
Pengaruh Political Connection Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Arogansi yang diukur dengan melihat adanya CEO pada suatu perusahaan sebagai seorang dalam politik atau politisi (Simon et. al., 2015). Political connection dapat diteliti melalui CEO dan dewan komisaris yang menjadi objek penelitian pada suatu perusahaan. adanya multi peran yang jalankan CEO maupun dewan komisaris dapat membantu bisnis suatu perusahaan dengan memanfaatkan jabatannya sebagi bentuk relasi dan koneksi yang lebih. Arrogance atau arogansi dapat menjadi salah satu indikasi terjadinya kecurangan terhadap laporan keuangan. Hal ini karena adanya anggapan bahwa kontribusi yang telah mereka lakukan dapat membantu kelancaran bisnis yang dijalankan perusahaan.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aidil dan Kurnia (2017) yang menyatakan bahwa hubungan politik atau political connetion berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Zelin (2018) menunjukkan bahwa political connection memiliki tidak pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka digunakan hipotesis:
H5: political connection berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
Pengaruh Financial Target Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Financial Target merupakan salah satu elemen dari Pressure yang dimana pihak manajer dituntut untuk menjaga target keuangan terhadap apa yang sudah direncanakan. Maka hal ini pihak manajer memiliki berpotensi untuk melakukan praktik kecurangan yang disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak manajer sehingga manajer memungkinkan dapat memanipulasi hasil keuangan agar sesuai atau melebihi target.
Skousen et al., (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel financial target berpengaruh positif Terhadap Laporan Keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tiffani (2015), Sihombing dan Raharja (2014) menemukan financial target tidak berpengaruh Terhadap Laporan Keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka digunakan hipotesis:
H6: Financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
Pengaruh Financial Stability Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Perusahaan yang baik akan menunjukkan kondisi keuangan yang cenderung stabil karena dalam hal ini menjadi salah satu strategi perusahaan dalam menarik investor. Aliran dana dan investasi perusahaan yang mengalir kedalam perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, maka hal ini mendukung adanya faktor pressure dimana pihak manajer akan tertekan dan berpotensi untuk memanipulasi laporan keuangan supaya terlihat stabil sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.
Hasil penelitian Tiffani dan Marfuah (2015) dan Sihombing (2014) menyatakan bahwa financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arisandi (2017) menemukan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka digunakan hipotesis:
H7 : Financial stability berpengaruh terhadap terhadap kecurangan laporan keuangan
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandas pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau secara statistik, bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah ditetapkan.
Gambaaran dari Populasi (Objek Penelitian)
Penelitian ini menetapkan populasi atau objek penelitian dengan mengacu pada data dari perusahaan sektor agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2019.
Teknik Pengambilan Sampel
Popilasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel yang bertujuan (Purposive Sampling) yaitu Teknik pengambilan sampel yang menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah kriteria yang digunakan oleh peneliti untuk pengambilan populasi yang digunakan pada penelitian ini: (1) Perusahaan Agrikultur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2019, (2) Perusahaan Agrikultur yang menerbitkan annual report secara berturut-turut selama periode 2016-2019. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh data sebanyak 18 perusahaan selama 4 tahun pengamatan yaitu dari tahun 2016-2019 dengan jumlah 72 firm years.
Teknik Pengambilan Data Jenis dan Sumber Data
Penelian ini menggunakan jenis data yang dihimpun dalam bentuk dokumenter. Data dokumenter merupakan jenis data penelitian dimana dalam penelitian ini mengumpulkan data yang diperlukan dapat dilakukan dengan menggunakan literatur yaitu laporan tahunan yang yang diterbitkan oleh perusahaan sampel yang juga memuat laporan keuangan perusahaan agrikultur periode tahun 2016–2019.
Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data sekunder. Menurut Murtanto (2016) Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dengan media perantara dan bukan peneliti yang melakukan studi secara mutakhir. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan keuangan tahunan perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Variabel Penelitian
Variabel Dependen
Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting dapat diukur dengan menggunakan fraud score model atau bisa disebut dengan f–score, yang dikembangkan oleh Dechow et al., (2011). Menurut Skousen (2009) Model F-score merupakan penjumlahan dari dua komponen variabel yaitu kualitas akrual (Accrual Quality) dan kinerja keuangan (financial performance). Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:
F – Score = Accrual Quality + Financial Performance
Accrual Quality atau kualitas akrual dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan RSST accrual (Richardson et al., 2005) sedangkan untuk financial performance atau kinerja keuangan dapat dihitung dengan perubahan pada akun piutang, perubahan akun penjualan secara tunai dan perubahan pada pendapatan sebelum bunga dan pajak.
RSST Accrual = (∆WC + ∆NCO + ∆FIN) / Average Total Assets
Keterangan:
WC (Working Capital) : (Current Assets – Current Liability)
NCO (Non Current Operating Accrual) : (Total Assets – Current Assets – Investment and Advances) – (Total Liabilities – Current Liabilities – Long Term Debt)
FIN (Financial Accrual) : Total Investment – Total Liabilities
ATS (Average Total Assets) : (Beginning Total Assets + End Total Assets)/2
Financial Performance = change in receivable + change in inventories + change in cash sales + change in earnings
Keterangan:
Change in Receivable : Δ Piutang / Rata – rata Total Aset
Changes in Inventory : Δ Persediaan / Rata – rata Total Aset
Changes in Cash Sales : (Δ Penjualan / Penjualan (t)) – (Δ Piutang / Piutang (t))
Changes in Earnings : (Laba (t) / Rata – rata Total Aset (t)) – (Laba (t – 1) / Rata – rata Total Aset (t – 1))
Variabel Independen
Kesempatan/peluang (Opportunity)
Terdapat dua faktor yang digunakan pada variabel opportunity yaitu nature of industry dan ineffective monitoring, berikut penjelasannya: Pengaruh Industri (Nature of Industry) merupakan keadaan ideal pada suatu perusahaan dalam industri. Perusahaan akan cenderung menekan jumlah piutang dan akan melakukan penerimaan kas yang lebih banyak, hal ini dilakukan agar perusahaan ingin terlihat baik (Sihombing dan Rahardjo, 2014). Pada akun piutang yang mungkin dilakukan manipulasi adalah piutang tak tertagih dan persediaan yang usang. Peneliti menggunakan rasio total piutang sebagai ukuran dari Natue of induustry, rumus yang digunakan Skousen (2009) sebagai berikut:
RECEIVABLE = (Receivable (t) / Sales (t) – (Receivable (t – 1) / Sales (t-1))
Ketidak efektifan pengawasan (ineffective monitoring) merupakan keadaan perusahaan yang mana terdapat pengendalian internal yang kurang baik sehingga terdapat pengawasan yang lemah. Kondisi tersebut dapat menciptakan peluang atau celah untuk oknum yang akan melakukan tindakan yang tidak benar untuk kepentingan pribadi. Pada penelitian ini ineffective monitoring diukur dengan menggunakan rasio jumlah komisaris independen (IND) (Skousen et al., 2009).
IND = Jumlah anggota dewan komisaris independen / total dewan komisaris
Kemampuan (Capability)
Capabilty merupakan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki seseorang, dimana hal ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki kemampuan dalam mengambil keuntungan pada kondisi–kondisi tertentu yang memungkinkan untuk melakukan kecurangan. Pergantian direksi (change in directors) yang dilakukan oleh perusahaan dapat menyebabkan stress period yang menciptakan peluang untuk melakukan fraud, adanya perubahan CEO atau direksi dapat diindikasi terjadi kecurangan (Wolfe dan Hermanson, 2004). Variabel tersebut dapat menggunakan metode dummy yang mana apabila perusahaan terdapat pergantian direksi selama periode pengamatan maka akan diberi kode angka 1, namun apabila selama periode pengamatan tidak terdapat pergantian direksi maka diberi kode 0.
Rasionalisasi (Rationalization)
Rasionalisasi merupakan sikap yang merasionalisasikan atau membenarkan suatu tindakan yang tidak semestinya. Pergantian auditor yang dilakukan perusahaan dapat dinilai sebagai bentuk untuk menghilangkan jejak kecurangan yang mungkin telah diketahui oleh auditor yang sebelumnya mengaudit perusahaan tersebut, sehingga mengganti auditor dilakukan untuk menutupi kecurangan yang mungkin telah dilakukan oleh perusahaan (Sihombing dan Rahardjo, 2014). Rationalization pada penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan pergantian auditor yang telah dilakukan oleh perusahaan yang diukur dengan menggunakan motode dummy yaitu menggunakan kode angka 1 apabila perusahaan terdapat perubahan Kantor Akuntan Publik (KAP) setiap tahunnya pada periode 2016 – 2019 dan kode 0 apabila perusahaan tersebut tidak terdapat perubahan Kantor Akuntan Publik selama periode pengamatan.
Arogansi (Arrogance)
Arogansi merupakan sifat superioritas atas hak yang dimiliki oleh seseorang dan merasa bahwa pengendalian internal perusahaan serta kebijakan tidak dapat berlaku untuk dirinya (Crowe, 2011). Sikap arogan tersebut biasanya lebih ditujukan kepada seseorang yang memiliki kedudukan tinggi didalam suatu perusahaan. Penelitian ini melakukan pengukuran variabel arrogance yang di proksikan proksikan dengan political connection. Menurut Kurnia dan Anis (2017) CEO dan dewan komisaris dapat menggunakan kekuatan politik yang dapat mereka lakukan pada saat perusahaan sedang mengalami masa sulit. Pada variabel political connection peneliti menggunakan metode dummy, yang mana akan diberi kode angka 1 apabila perusahaan tersebut pada jajaran direksi maupun komisaris memiliki hubungan politik selama periode pengamatan, apabila tidak terdapat hubungan politik selama periode pengamatan tersebut maka diberi kode 0.
Tekanan (Preassure)
Tekanan dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan karena beban keuangan (Shelton, 2014) Preassure pada penelitian ini diukur dengan menggunakan dua ukuran yaitu financial target dan financial stability, dengan penjelasan sebagai berikut: Target Keuangan (financial target) merupakan target keuangan yang harus dicapai oleh perusahaan mengenai kinerja keuangan seperti target laba yang harus dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu. Financial target pada penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas dalam analisis laporan keuangan atau kinerja perusahaan yang menghitung rasio laba pada aset (Skousen et al, 2008). ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
ROA = Earnings After Interest and Tax / Total Assets
Stabilitas keuangan (financial stability) merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan stabil. Salah satu kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat melalui bagaimana kondisi aset perusahaan dimana pertumbuhan perubahan aset perusahaan cenderung memungkinkan seseorang untuk melakukan manipulasi pada bagian tersebut (Skousen, 2009). Penelitian ini menggunakan ACHANGE yang merupakan rasio perubahan aset pada laporan keuangan perusahaan yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
ACHANGE = (Total Aset (t) – Total Aset (t-1)) / Total Aset (t-1)
Teknik Analisis Data
Uji Asumsi Klasik
Uji pada regresi suatu penelitian dapat dilakukan apabila telah memenuhi uji asumsi klasik yang baik. Uji asumsi klasik sendiri dilakukan untuk mendeteksi adakah data yang menyimpang dari asumsi klasik dari persamaan regresi yang akan digunakan (Sihombing, 2014). Penelitian ini untuk menguji asumsi klasik yang terdiri dari; uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heterokedastisitas.
Uji Normalitas
Uji normalitas data penting dilakukan dimana dalam uji ini digunakan agar dapat mengetahui apakah data yang akan digunakan telah terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menerapkan dua metode yaitu uji Kolmogorov–Smirnov Test dan grafik Probability plot. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov– Smirnov Test dengan melihat hasil apabila signifikansi senilai >0,05 maka data telah terdistribusi normal.
Uji Multikolonieritas
Model regresi yang baik adalah tidak terdapat korelasi diantar variabel independen (Ghozali, 2013). Uji multikolonieritas dilakukan sebagai alat penguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen yang dapat dilihat dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance dengan kriteria penelitian ini sebagai berikut:
Jika nilai tolerance ≥ 0,10 atau nilai VIF ≤ 10, maka tidak terjadi multikolonieritas.
Jika nilai tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10, maka terjadinya multikolonieritas.
Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan sebagai pendeteksi adanya ketidakseimbangan variance dari residual pada model regresi. Apabila suatu penelitian yang menggunakan model regresi menunjukan adanya heteroskedastisitas maka dinyatakan tidak baik. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat melihat pola yang dihasilkan grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X merupakan residual yang telah di studentized.
Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran secara informatif dengan penyajian data yang mengelompok dan lebih ringkas. Pengukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif data dapat meliputi rata–rata (mean), varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis sweknes dan standar deviasi (Ghozali, 2016). Data yang diteliti dengan analisis statistic deskriptif pada penelitian ini terdiri dari variabel independen berupa elemen atau komponen dari fraud pentagon yaitu meliputi opportunity, capability, rationalization, arrogance dan preassure, serta variabel dependen yang digunakan yaitu kecurangan laporan keuangan.
Uji Hipotesis dan Analisis Data
Uji hipotesis dan analisis data pada penelitian ini menerapkan bentuk analisis regresi linier berganda untuk mengukur adanya hubungan kedua variabel tersebut yaitu variabel independen terhadap variabel dependen dengan alat bantu software SPSS 24. Penggunaan F– Score model untuk mengukur kecurangan laporan keuangan (Kurnia dan Anis, 2017).
F–SCORE = a + β1RECEIVABLE + β2IND + ß3 ΔCID + ß4 ΔCIA + β5 POLITICAL + ß6ROA + ß7ACHANGE + ε
Keterangan:
F-Score : Kecurangan laporan keuangan
A : Konstanta
RECEIVABLE : Rasio total piutang terhadap pendapatan operasional
IND : Rasio dewan komisaris independen
∆CID : Pergantian jajaran direksi perusahaan
∆CIA : Pergantian auditor independen
POLITICAL : Jajaran direksi dan komisaris yang memiliki hubungan politik
ROA : Return on asset
ACHANGE : Rasio perubahan total asset
ε : Eror
Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Uji koefisien determinan (Adjusted R2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan varian variabel independen. Menurut Ghozali (2013) apabila nilai Adjusted R2 mendekati angka 1 (satu) menunjukan bahwa variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen tersebut:
Nilai Adjusted R2 yang kecil menunjukan kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi dependen nilai sangat kecil.
Nilai Adjusted R2 yang mendekati 1 (satu) menunjukan bahwa variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen.
Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji Kelayakan Model atau Uji F digunakan dalam menguji model yang akan digunakan untuk melakukan analisis regresi tersebut telah baik. Uji F juga digunakan untuk menguji signifikansi dengan melihat tingkat nilai signifikansi F pada output hasil regresi yang disajikan tabel ANOVA. Apabila nilai signifikansi menunjukan nilai yang lebih besar dari 0,05 maka model regresi tersebut tidak baik (tidak fit), dan apabila nilai model regresi lebih kecil dari 0,05 menunjukan nilai regresi tersebut baik atau dalam kondisi fit (Ghozali, 2013).
Uji Hipotesis (Uji t)
Uji hipotesis atau Uji t pada model regresi penelitian ini digunakan untuk mengetahui signifikansi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Widjarjono (2015) menyatakan uji hipotesis dua sisi akan dipilih jika tidak memiliki dugaan kuat atas dasar teori yang digunakan dalam penelitian, sebaliknya apabila hanya memilih salah satu sisi maka peneliti telah memiliki landasan teori atau dugaan teori yang kuat pada penelitiannya. Berikut merupakan cara mengambil keputusan dalam menentukan hipotesis dapat diterima atau ditolak:
Nilai probabilitas < α, maka H0 ditolak, H1 diterima.
Nilai probabilitas > α, maka H0 diterima, H1 ditolak.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi klasik pada penelitian ini dengan melakukan beberapa tahapan diantaranya terdiri dari; uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heterokedastisitas. Berikut merupakan hasil dari masing–masing uji yang telah dilakukan.
Uji Normalitas
Uji normalitas pada penelitian ini menerapkan dua metode yaitu uji Kolmogorov- Smirnov Test dan grafik Probability plot. Pertama, Uji normalitas menggunakan Kolmogorov– Smirnov Test dengan melihat hasil apabila signifikansi senilai >0,05, maka data dapat dikategorikan telah terdistribusi.
Tabel 1
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 72
Normal Parametersa,b
Mean 0.0000000
Std. Deviation 1.30693221
Most Extreme Differences
Absolute 0.162
Positive 0.115
Negative -0.162
Kolmogorov-Smirnov Z 0.162
Asymp. Sig. (2-tailed) .098
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-smirnov test diatas menunjukan bahwa nilai Asymp.-Sig. (2-tailed) atau angka probabilitas signifikasi sebesar 0,098 yang nilainya lebih besar dari 0,05 (>5%) menunjukan bahwa variabel penelitian terdistribusi normal.
Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas dilakukan sebagai alat penguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen, maka untuk mengetahui ada atau tidak ada multikolonieritas suatu data penelitian dapat dilihat dengan nilai VIF <10 dan Tolerance >0,10. Pada penelitian ini hasil uji multikolineritas disajikan sebagai berikut:
Tabel 2
Uji Multikonieritas
Collinearity Statistics
Model — Tolerance — VIF
Receivable — 0.874 — 1.144
IND — 0.841 — 1.189
CID — 0.909 — 1.100
CIA — 0.860 — 1.163
Politik — 0.807 — 1.239
ROA — 0.423 — 2.366
ACHANGE — 0.406 — 2.465
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan dari hasil uji multikolinearitas diatas, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini sudah terbebas dari adanya multikolinearitas dengan nilai semua variabel independen menunjukkan angka VIF <10 dan nilai tolerance >0,10.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan sebagai pendeteksi adanya ketidakseimbangan variance dari residual pada model regresi. Apabila suatu penelitian yang menggunakan model regresi menunjukan adanya heteroskedastisitas maka dinyatakan tidak baik. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat melihat pola yang dihasilkan grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X merupakan residual yang telah di studentized.
Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan dari hasil uji heteroskedastisitas di atas, menunjukkan bahwa grafik scatterplot pada penelitian ini titik – titik data telah menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran secara informatif dengan penyajian data yang mengelompok dan lebih ringkas. Pengukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif data dapat meliputi rata–rata (mean), varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis sweknes dan standar deviasi (Ghozali, 2016).
Tabel 3
Descriptive Statistics
Receivable — N 72 — Minimum -0.171 — Maximum 0.134 — Mean 0.001 — Std. Deviation 0.049
IND — N 72 — Minimum 0.200 — Maximum 0.800 — Mean 0.392 — Std. Deviation 0.098
CiD — N 72 — Minimum 0.000 — Maximum 1.000 — Mean 0.306 — Std. Deviation 0.464
CiA — N 72 — Minimum 0.000 — Maximum 1.000 — Mean 0.264 — Std. Deviation 0.444
Politik — N 72 — Minimum 0.000 — Maximum 1.000 — Mean 0.208 — Std. Deviation 0.409
ROA — N 72 — Minimum -1.015 — Maximum 0.262 — Mean -0.016 — Std. Deviation 0.174
ACHANGE — N 72 — Minimum -3.616 — Maximum 0.719 — Mean -0.039 — Std. Deviation 0.463
F-Score — N 72 — Minimum -7.636 — Maximum 3.452 — Mean 0.006 — Std. Deviation 1.435
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
⸻
Uji Koefisien Determinasi (R²)
Uji koefisien determinan (Adjusted R²) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan varian variabel independen. Nilai pada Adjusted R² adalah berada diantara 0 dan 1 (0 < R² < 1). Nilai R² relatif kecil memiliki kemampuan yang terbatas ketika variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi:
Tabel 4
Hasil Koefisien Determinasi (Model Summary)
R = .513
R Square = 0.340
Adjusted R Square = 0.091
Std. Error of the Estimate = 1.37655
Durbin-Watson = 2.085
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan tabel di atas menunjukan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,340 yang menunjukan bahwa variabel Kecurangan Terhadap Laporan Keuangan dapat dipengaruh oleh Natural of Industry, Ineffective Monitoring, Change in Directors, Chenge in Auditor, Political Connection, Financial Target dan Financial Stability sebesar 34% dan selebihnya sebesar 66% dipengaruhi oleh faktor atau variabel diluar penelitian ini.
Uji Kelayakan Model (Uji F)
Hasil uji Kelayakan Model atau Uji F digunakan dalam menguji model yang akan digunakan untuk analisis regresi biasanya ditunjukkan pada tabel ANOVA yang terdapat pada hasil olah data menggunakan SPSS. Apabila nilai signifikansi menunjukan nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai standar statistik 0,05. Berikut hasil dari perhitungan Uji F:
Tabel 5
ANOVA
Regression Sum of Squares = 24.880 — df 7 — Mean Square 3.554 — F 15.678 — Sig .000
Residual Sum of Squares = 121.273 — df 64 — Mean Square 1.895
Total Sum of Squares = 146.153 — df 71
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan tabel hasil Uji F diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi pada penelitian ini sebesar 0,000 < 0,05 maka telah sesuai dengan syarat pengambilan keputusan pada uji F, yang dapat disimpulkan bahwa nilai regresi pada penelitian ini bersifat fit.
Uji Hipotesis (Uji t)
Pengujian hipotesis ditunjukkan untuk mengukur hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Berikut merupakan tabel hasil uji hipotesis:
Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis (Coefficients)
(Constant) — B 0.493 — Sig 0.507
Receivable — B 5.691 — Sig 0.130
IND — B -0.902 — Sig 0.559
CID — B -0.148 — Sig 0.392
CIA — B -0.047 — Sig 0.587
Politik — B 0.654 — Sig 0.280
ROA — B 4.749 — Sig 0.002
ACHANGE — B -1.205 — Sig 0.016
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan hasil uji regresi diatas maka dapat dihasilkan persamaan regresi berikut ini:
F–SCORE = 0,493 + 5,691 RECEIVABLE + -0,902 IND + -0,148 ΔCID + -0,047 ΔCIA + 0,654 POLITICAL + 4,749 ROA + -1,205 ACHANGE + ε
Pembahasan
Pengaruh Nature Of Industry Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Pengujian hipotesis pada variabel Nature of industry penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikan. Hasil pengujian hipotesis pada variabel ini menunjukan bahwa Nature of industry menunjukan nilai sebesar 1,533 dan sig. t 0,130 >0,05 yang artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sehingga hipotesis 1 ditolak, karena semakin besar nilai pada variabel tersebut maka menunjukan potensi terjadi kecurangan pelaporan keuangan juga semakin tinggi. Variabel Nature of industry (RECIVABLE) pada penelitian ini menunjukan rasio perubahan piutang yang kurang stabil atau nilai rasio piutang pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 memiliki rasio yang relativ stabil. Pada tabel hasil analisis deskriptif variabel ini menunjukan nilai rata-rata sebesar 0,001, dengan nilai minimum sebesar -0,171, dan nilai maksimum sebesar 0,134.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiffani dan Marfuah (2015) dan Iqbal dan Murtanto (2016) serta Sasangko dan Wijayantika (2019) yang menyimpulkan bahwa variabel Nature of industry tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putriasih, Herawati dan Wayuni (2016) dan Devi (2020) yang menyatakan bahwa variabel nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
Ketika perusahaan berada dalam kondisi ideal, pihak manajemen tidak akan melakukan tindakan kecurangan terhadap pelaporan keuangan agar perusahaan terlihat dalam kondisi yang baik. Namun, ketika kondisi perusahaan dalam kondisi tidak ideal manajemen kemungkinan akan mengambil tindakan kecurangan hal ini dilakukan agar perusahaan terlihat baik dalam suatu industry (Agusputri dan Sofie, 2019). Bentuk tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen umumnya dengan cara melakukan salah saji material dan melibatkan akun-akun terkait dengan cara mengestimasi sehingga laporan keuangan dapat terlihat baik dimata investor.
Pengaruh Ineffective Monitoring Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Hasil pengujian hipotesis variabel Ineffective Monitoring dengan menggunakan proksi IND menunjukan nilai koefisien regresi sebesar -0,587 dengan sig.t 0,599 yang artinya lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Ineffective Monitoring pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sehingga hipotesis 2 (H2) ditolak. Variabel Ineffective Monitoring dikatakan tidak berpengaruh karena adanya pengawasan dari komisaris independen pada perusahaan agrikultur sudah efektif dan maksimal. Dewan komisaris independen yang berpedoman kepada prinsip GCG (Good Corporate Governance) telah melakukan fungsi pengawasan secara efektif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan baik.
Keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah komisaris independen tidak mempengaruhi tindakan manajemen dalam melakukan kecurangan laporan keuangan.
Pengaruh Change In Director Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Change in Director tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya nilai koefisien regresi sebesar -0,847 dan nilai sig.t sebesar 0,392 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 3 (H3) ditolak. Artinya, adanya pergantian direksi tidak menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan.
Pergantian direksi pada umumnya dilakukan karena adanya rotasi jabatan, penyesuaian strategi perusahaan, dan perbaikan kinerja perusahaan, bukan sebagai bentuk upaya untuk menutupi jejak kecurangan (fraud trail) yang telah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, perubahan susunan direksi tidak selalu berkaitan dengan praktik kecurangan laporan keuangan.
Pengaruh Change In Auditor Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel Change in Auditor menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,214 dengan nilai sig.t 0,587 yang lebih besar dari 0,05 (>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Change in Auditor tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dan hipotesis 4 (H4) ditolak.
Pergantian auditor yang terjadi pada perusahaan agrikultur umumnya disebabkan oleh rotasi audit, berakhirnya kontrak perjanjian kerja sama, atau kebijakan internal perusahaan dalam memilih auditor yang dianggap lebih sesuai. Oleh karena itu, pergantian auditor tidak dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya kecurangan pada laporan keuangan perusahaan.
Pengaruh Political Connection Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel Political Connection tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,935 dengan sig.t 0,280 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 5 (H5) ditolak.
Perusahaan dengan struktur manajemen dewan komisaris maupun dewan direksi di dalamnya yang memiliki hubungan politik belum tentu mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan aksi arrogance untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan terhadap laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena sikap profesionalisme kerja anggota manajemen perusahaan yang mampu mengendalikan tingkat arrogance yang memisahkan antara kepentingan internal perusahaan dengan kepentingan politik. Kemungkinan lain dapat disebabkan oleh kebijakan internal perusahaan untuk tidak mencantumkan jabatan atau hubungan politik yang dimiliki oleh anggota direksi maupun komisaris perusahaan.
Pengaruh Financial Target Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Variabel berikutnya adalah variabel pressure dihitung menggunakan financial target atau Return On Assets (ROA) yang merupakan hipotesis 6 (H6) pada penelitian ini. Setelah dilakukan pengujian maka menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 3,162 dan tingkat sig.t sebesar 0,002 < 0,05 artinya bahwa variabel financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6 (H6) diterima. Semakin besar tingkat target keuangan pada perusahaan dapat menimbulkan potensi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan semakin tinggi.
ROA merupakan rasio profitabilitas yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Variabel financial target pada penelitian ini menunjukan pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan yang dapat diartikan bahwa ROA yang ditargetkan perusahaan yang semakin tinggi dapat menyebabkan semakin besarnya potensi perusahaan melakukan manipulasi jumlah laba pada laporan keuangan.
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriasih (2016), Aprilia (2017), serta Septriani dan Handayani (2018) yang menyatakan bahwa financial target yang diukur menggunakan ROA berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. ROA dijabarkan sebagai sebuah bonus, return saham, kenaikan terhadap upah, sehingga ROA yang terlihat tinggi pada periode sebelumnya mengidentifikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu mencetak laba yang tinggi, sehingga menjadi acuan perusahaan untuk menetapkan target keuangan yang lebih tinggi di periode berikutnya.
Pengaruh Financial Stability Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
Variabel terakhir pada penelitian ini menggunakan financial stability yang merupakan hipotesis 7 (H7). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan nilai koefisien regresi sebesar -2,483 dan tingkat sig.t 0,016 < 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa variabel financial stability memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H7 diterima.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada variabel financial stability menunjukan nilai rata-rata sebesar 0,039 yang dapat diartikan bahwa rasio ACHANGE tinggi sehingga kondisi keuangan pada perusahaan terlihat kurang stabil dengan nilai minimum sebesar -3,616 dan nilai maksimum sebesar 0,719 yang menunjukan perubahan yang tinggi dan tidak stabil.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa pihak agent harus bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen perusahaan terhadap principal. Ketika adanya masalah agensi, yaitu kondisi perusahaan yang cenderung tidak stabil dapat menyebabkan pihak manajemen dalam posisi tertekan karena dampak penilaian kinerja yang buruk dan tidak dapat memaksimalkan aset perusahaan sebagaimana yang diharapkan oleh para pemegang saham.
Variabel financial stability pada penelitian ini memiliki hubungan dengan kecurangan laporan keuangan yang dapat diartikan apabila kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak stabil maka potensi kecurangan laporan keuangan juga akan meningkat. Skousen et al., (2009) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa stabilitas keuangan dapat tercermin dari rasio perubahan aset. Semakin besar rasio perubahan total aset atau menurunnya tingkat total aset dapat menyebabkan turunnya performa perusahaan sehingga kurang memberikan nilai return yang maksimal untuk investor karena kurang mampu memaksimalkan manajemen aset dan sumber dana investasi yang dimiliki perusahaan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2019, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Nature of Industry tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Ineffective Monitoring tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Change in Director tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
4. Change in Auditor tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
5. Political Connection tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
6. Financial Target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
7. Financial Stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
Keterbatasan
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disusun di atas, terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian ini pada variabel Arrogance hanya menggunakan indikasi hubungan politik sebagai metode perhitungan yang mana hasil yang diperoleh belum cukup kuat untuk dapat mencerminkan fraud pentagon pada penelitian yang dilakukan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel proksi, sehingga belum mampu menjelaskan secara menyeluruh faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kecurangan laporan keuangan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor agrikultur sebagai sampel sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sektor perusahaan.
4. Data annual report perusahaan agrikultur yang digunakan masih terdapat beberapa informasi yang kurang lengkap dari tahun ke tahun.
Saran
Penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan kriteria-kriteria yang dirasa paling diperlukan agar dapat menghasilkan jumlah perusahaan sampel yang lebih banyak dengan data annual report lengkap sehingga dapat memperkuat varian setiap pengujian yang dilakukan. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang relevan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.
DAFTAR PUSTAKA
ACFE. 2016. http://acfe-indonesia.or.id/wpcontent/uploads/2017/07/survai-fraud- indonesia-2016.pdf. 26 Oktober 2020.
———. 2018. Association of Certified Fraud Examiners—Fraud 101. http://www.acfe.com/fraud-101.aspx. 26 Oktober 2020
Agusputri, Hanifah dan Sofie. 2019. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Fraudulent Financial Reporting Dengan Menggunakan Analisis Fraud Pentagon. Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik 14(2): 105–124.
Aminoff, M. J., D. A. Dreenberg, dan R. P. Simon. 2015. Clinical Neurology. 9th ed. London.
Andarwanto, Andri. 2014. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit. Fakultas Ekonomi: Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
Aprilia. 2017. Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) 9(1): 101–132.
Atmadja, A. T., dan A. K. Saputra. 2017. Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 12(1), 7. https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02
Cahyanti, Devi dan Wahidahwati. 2020. Analisis Pentagon Sebagai Pendeteksi Kecurangan Terhadap Lapiran Keuangan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntasi 9(4): 1–24.
Cressey, D. 1953. Other people’s money, dalam: “Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Journal of Corporate Governance and Firm Performance 13(2): 53–81.
Crowe Horwath. 2010. IIA Practice Guide: Fraud and Internal Audit. Crowe LLP. New York.
———. 2011. Why the fraud triangle is no longer enough. Orwath: Crowe LLP. New York.
Gamayuni, R. R., 2015. The effect of intangible asset, financial performance and financial policies on the firm value. International Journal Of Scientific & Technology Research 4(1): 202–212.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
———. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Harto, Puji. dan Chyntia Tessa G. 2016. Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon Pada Sektor Keuangan Dan Perbankan Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung.
Iqbal, M., dan Murtanto. 2016. Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Seminar Nasional Cendekiawan 17(2): 1–17.
Jensen, Michael C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3(5): 305–360.
Kurnia, Aidil A., dan Anis, Idrianita. 2017. Analisis Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Fraud Score Model. Simposium Nasional Akuntansi XX. Jember.
Kurniawan, A. 2017. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Financial Distress Melalui Terjadinya Fraud. Jurnal Akuntansi Manajemen 6(2): 152–166.
Laila, M. Tiffani. 2015. Determinan financial statement fraud dengan analisis fraud triangle pada entitas manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013–2015. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 19(7): 1–12.
Lintner, J. 1956. Distribution of Incomes of Corporation among Dividends, Retained Earnings, and Taxes. The American Reviews. New York.
Maria Ni Luh Susanti dan Gerianta Wirawan Yasa. 2013. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pemoderasi Good Corporate dan Corporate Social Responsibility. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3(1): 73–91.
Martantya, Daljono. 2013. Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko Tekanan dan Peluang. Dipenogoro Journal of Accounting 2(2): 1–12.
Nugraheni, Nella Kartika. 2017. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya financial statement fraud: perspektif diamond theory. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Nugraheni, Nella Kartika, dan Hanung Triatmoko. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Financial Statement Fraud: Perspektif Diamond Fraud Theory (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014–2016). Jurnal Akuntansi dan Auditing 14(2): 118–143.
Putriasih, K., N. N. T. Herawati, dan M. A. Wahyuni. 2016. Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha 6(3): 1–12.
Putriasih, Ketut. 2016. Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012–2014. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
Richardson, Elizabeth E., George Papandonatos, dan Alessandra Kazura. 2005. Differentiating Stages of Smoking Intensity Among Adolescents: Stage Specific Psychological and Social Influences. Journal of Consulting and Clinical Psychology 70(4): 998–1109.
Sasongko, N., S. F. Wijayantika. 2019. Faktor Resiko Fraud terhadap Pelaksanaan Fraudulent Financial Reporting (Berdasarkan Crown’s Fraud Pentagon Theory). Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 12(4): 14–29.
Septriani, R., dan S. R. Handayani. 2018. Pengaruh Return On Equity (ROE), Debt To Equity Ratio (DER), Dan Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Price Earning Ratio (PER) (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011–2016). Jurnal Administrasi Bisni 65(1): 46–54.
Sihombing, Kennedy Samuel dan Siddiq Nur Rahardjo. 2014. Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Di Indonesia (BEI) Tahun 2010–2012. Diponegoro Journal of Accounting 3(2): 1–12.
Skousen, J. C., dan Smith R. Kevin. 2009. Detecting and Predicting Kecurangan Laporan Keuangan: The Effectivensess of The Fraud Triangel dan SAS No. 99. Corporate and Firm Performance Advances in Financial Economics 13(1): 53–81.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
Summers, S. dan J. Sweeney. 1998. Fraudulently misstated financial statements and insider trading: An empirical analysis. The Accounting Review 3(1): 131–146.
Tessa, G. C. dan P. Harto. 2016. Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon pada Sektor Keuangan dan Perbankan di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIX: 1–21. Medan.
Triyanto, D. N. 2020. Detection of Financial Reporting Fraud: The Case of Socially Responsible Firms. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura 22(3): 399–410.
Widjarjono, A. 2015. Statistika Terapan dengan Excell dan SPSS (1st ed). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Wolfe, D. T., dan D. R. Hermanson. 2004. The Fraud Diamond: Consindering the Four Element of Fraud. CPA Journal 74(12): 38–42.
Zelin, Cintia. 2018. Analisis Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Fraud Score Model. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
Penulis adalah Anggota IKPI Cabang Surabaya
Danny Wibowo dan Yusril Putra
Email: yusrilputra26@gmail.com
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis
Catatan: Tulisan ini pernah dipublikasikan pada ACFE/Riset dan Jurnal Akuntansi (SINTA 3) Tahun 2023