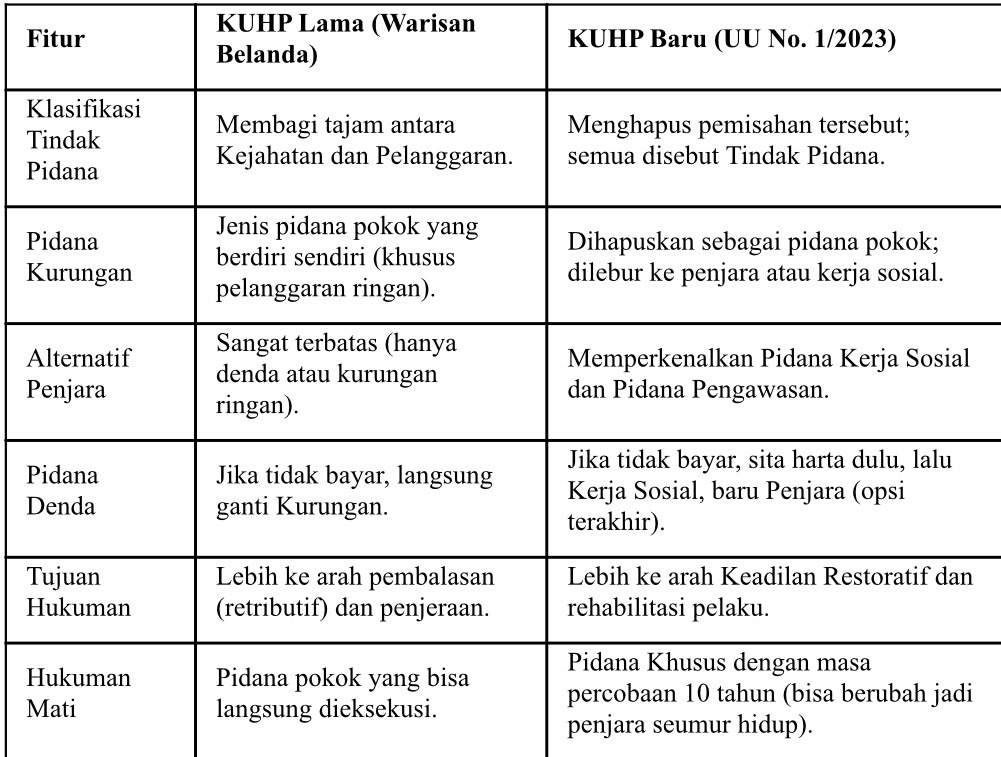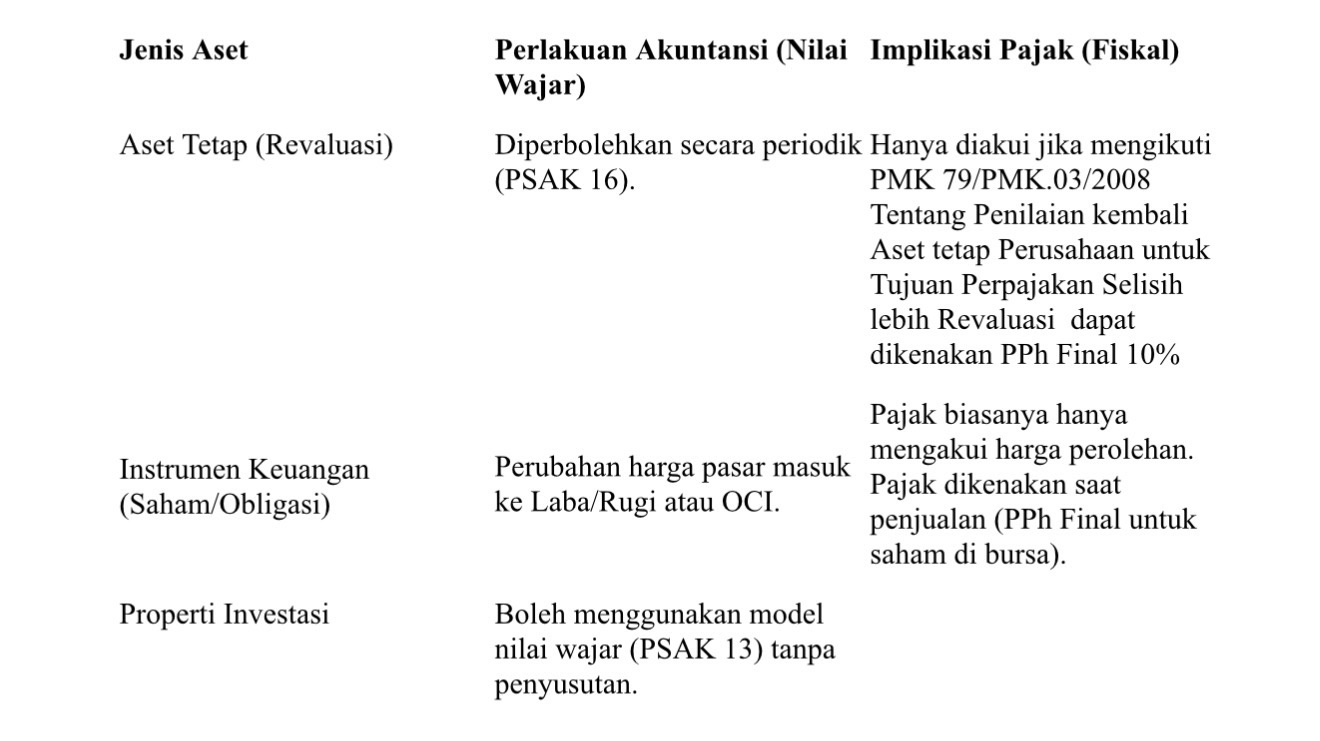ABSTRACT
Berdasarkan uraian diatas bahwa modal sosial di Indonesia sangat berpengaruh besar bagi pengusaha kena pajak terhadap perubahan regulasi PPN. Adanya keberagaman pada masyarakat Indonesia ini membuat peneliti sangat tertarik untuk membahasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang respon pelaku usaha atas peraturan perpajakan khususnya PPN yang dilakukan oleh PKP dalam upaya mempertahankan usahanya dengan memaksimalkan nilai-nilai modal sosial yang dimiliki.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Penelitian dilakukan pada empat distrik yang berbeda di Provinsi Nusa tenggara Timur Larantuka, Waiwerang, Lembata & Maumere. Untuk memperoleh informasi peneliti melakukan pengamatan lapangan dan wawancara. Informan memanfaatkan modal sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial dengan relasinya dalam berbagai tindakan sosial baik dengan masyarakat sekitar, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pelanggan. Hubungan ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam kegiatan ekonomi. Sebagai upaya menjaga kelangsungan usaha pemanfaatan modal sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial berupa hubungan kekerabatan, kepercayaan, nilai dan norma.
Keywords: PKP, VAT, Social Capital, Business Continuity
PENDAHULUAN
Sejak tahun 1984 Indonesia telah menerapkan Self Assessment System yang berarti memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak mulai dari mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Pemberlakuan self assesment system ini bertujuan kepada para Wajib Pajak mempunyai tanggung jawab, kesadaran diri dan kejujuran dalam melakukan kewajibannya agar patuh pada hukum perpajakan. Selain itu, self assesment system juga meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Wajib Pajak tidak secara sukarela membayar pajak sehingga mereka melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi beban pajak mereka (Celikay, 2020).
Setidaknya perilaku ketidakpatuhan wajib pajak ada empat yaitu sikap, norma subjektif, kewajiban moral, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan artinya perilaku wajib pajak juga terdapat norma-norma sosial yang berlaku di sekitarnya terutama bagi para pelaku usaha yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap kewajibannya atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP wajib mengenakan pajak atas penyerahan barang dan jasa dengan konsumen, maka dari situ timbul kenaikan harga jual yang diterapkan. Hal tersebut memungkinkan Wajib pajak akan melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban PPN wajib pajak.
Kecenderungan seseorang dalam berperilaku terdapat adanya kepercayaan atau keyakinan dalam diri individu terhadap seseorang yang menjadi referensinya, misalnya rekan, sanak saudara, serta kerabat terdekat (Sinarwati et al., 2019). Sikap percaya ini dapat menciptakan hubungan individu dengan individu lain, kelompok dan masyarakat yang lebih luas, sehingga hubungan ini merupakan salah satu aspek dalam modal sosial.
Dalam modal sosial, kepercayaan menjadi elemen yang penting karena didalamnya terdapat ikatan sosial dan saling percaya antar individu dengan lembaga. Hal ini dapat tercermin dari kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi penting disamping regulasi yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesaling-percayaan sebagai upaya mengelola modal sosial yang bermanfaat untuk mendukung keberlanjutan usaha.
Indeks Modal Sosial yang ada Indonesia tentunya beragam, hal ini disebabkan karena adanya berbagai macam ras, suku, dan budaya di setiap wilayah (Sinarwati et al., 2019). Keanekaragaman budaya tersebut menyebabkan adanya perbedaan perilaku antara masyarakat di lingkungan kota dengan masyarakat di lingkungan pedesaan. Misalnya kebiasaan masyarakat di suatu tempat yang menjunjung tinggi religiusitas akan berbeda dengan kebiasaan masyarakat di tempat lainnya juga berlaku dalam urusan perpajakan. Namun seiring dengan berkembangnya norma sosial di masyarakat Indonesia, maka dapat berdampak pada perilaku individu sehingga juga berdampak secara khusus pada perilaku kepatuhan pajak di Indonesia (Permata & Kristanto, 2020). Namun jika para wajib pajak dengan sikap moral tertentu akan beranggapan bahwa pajak merupakan sesuatu yang tidak penting, sehingga dapat menjalankan penghindaran pajak (Zhang & Cain, 2017). Dengan begitu wajib pajak akan terus berusaha mencari celah membayarkan pajak dalam jumlah yang sekecil-kecilnya dan menghindari pembayaran pajak yang besar.
Berdasarkan uraian diatas bahwa modal sosial di Indonesia sangat berpengaruh besar bagi pengusaha kena pajak terhadap perubahan regulasi PPN. Adanya keberagaman pada masyarakat Indonesia ini membuat peneliti sangat tertarik untuk membahasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang respon pelaku usaha atas peraturan perpajakan khususnya PPN yang dilakukan oleh PKP dalam upaya mempertahankan usahanya dengan memaksimalkan nilai-nilai modal sosial yang dimiliki.
STUDI LITERATUR
Peningkatan kepatuhan sukarela terhadap undang-undang perpajakan suatu negara tampaknya paling erat kaitannya dengan demokrasi yang sehat di mana watak budaya dan norma hukum mendorong toleransi, kerja sama, dan rasa tanggung jawab pribadi dan sosial untuk orang lain (Santoso et al., 2019).
Interaksi sosial baik bersifat ekonomi ataupun non-ekonomi ditentukan dengan adanya kepercayaan dari pihak-pihak yang ada. Terdapat potensi kelompok dan pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok yang menjadi norma kelompok tersebut (Kragh, 2016). Modal sosial khususnya keragaman budaya yang dimiliki oleh pengusaha akan menimbulkan perbedaan sikap terhadap perpajakan (Permata & Kristanto, 2020).
Modal sosial menurut Putnam (2015) bahwa tiap individu dalam kelompok telah memiliki ikatan timbal balik dan kepercayaan. Dengan adanya modal sosial ini maka seseorang akan memiliki beberapa keuntungan atau privilege. Yong et al., (2019) berpendapat kelompok dapat menjadi sumber keuangan dan sumber daya manusia untuk berwirausaha dikarenakan adanya hubungan kekerabatan. Teori norma sosial berpendapat bahwa perilaku individu sering kali dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana anggota lain dalam suatu kelompok berpikir dan bertindak termasuk dalam urusan perpajakan (Salmivaara et al., 2021).
Peran modal sosial dapat dikatakan penting untuk kehidupan bermasyarakat lantaran merupakan aset sosial yang memungkinkan individu dan masyarakat bekerja lebih efisien. Menurut Putnam (2015) modal sosial merupakan komponen organisasi sosial yang meliputi kepercayaan, norma, serta jaringan yang dapat menumbuhkan efisiensi dalam bermasyarakat.
Modal sosial mendorong penguatan individu, kolektifitas, organisasi dan negara dalam menjalankan interaksi yang berulang melalui jaringan, kepercayaan dan norma. Jaringan membentuk modal sosial sebagai saluran arus informasi yang bermanfaat untuk memfasilitasi pencapaian tujuan (Baykal & Hesapci, 2022).
Robert D. Putnam menganalogikan modal sosial sama dengan modal sosial lainnya, seperti modal fisik dan pendidikan sebagai modal manusia. Menurut Putnam (2015) ide inti dari teori modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai. Jaringan yang membentuk modal sosial juga berfungsi sebagai saluran informasi yang memfasilitasi pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Kepercayaan, norma dan jaringan sosial adalah konsep inti dalam modal sosial (Baykal & Hesapci, 2022).
Putnam (2015) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu fitur organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Modal sosial mengacu pada hubungan antara individu-individu serta jaringan sosial dan norma-norma juga kepercayaan sehingga ia beranggapan bahwa jejaring sosial memiliki nilai dan kontak sosial mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok (Putnam, 2015)
METODE
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan informasi historis, mengamati fenomena dan mendegarkan langsung pengalaman-pengalaman lapangan individual tertentu berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Penelitian dilakukan pada empat distrik yang berbeda di Provinsi Nusa tenggara Timur; Larantuka, Waiwerang, Lembata & Maumere yang dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2022. Untuk memperoleh informasi peneliti melakukan pengamatan lapangan dan wawancara kepada informan yang relevan.
Wawancara dilakukan dengan persetujuan informan dan dilakukan lebih dari satu kali dengan waktu dan kondisi yang berebeda, hal ini peneliti lakukan selain karena keterbatasan waktu dari para informan juga sebagai bahan evaluasi dan analisis singklonisasi atas informasi yang diperoleh dari fenomena dan pertanyaan penelitian. Namun dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang sedang terjadi maka dalam proses wawancara ini dilakukan secara daring yakni melalui aplikasi zoom virtual meeting (daring) namun untuk beberapa sesi wawancara berikutnya peneliti melakukan wawancara secara tatap muka (luring) dan melihat langsung kondisi lapangan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif lebih kepada fenomenologi yang terjadi pada lingkungan target penelitian. Jenis Fenomenologi tidak terbatas pada kehidupan dari individu tetapi lebih pada konsep atau fenomena. Sebuah studi fenomenologis menggambarkan makna bagi beberapa individu mengenai pengalaman bersama mereka tentang sebuah konsep atau fenomena Creswell (2015) dalam bentuk deskriptif dengan fokus penelitian berkaitan atas fenomena perubahan regulasi PPN sebagai PKP dalam memanfaatkan modal sosial yang dimiliki.
HASIL
Eksistensi Modal Sosial
Modal sosial dianggap sebagai aset penting di kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam konteks ini modal sosial tidak diartikan hanya sebatas modal berbentuk uang atau harta kekayaan, melainkan keseluruhan sumber daya berunsur sosial yang dimiliki masyarakat terurama bagi para pelaku usaha. Hubungan sosial merupakan tindakan saling mengakui dan saling mengenal antar manusia, sehingga dalam hubungan tersebut dapat terbangun relasi, kepercayaan, solidaritas, dan membantu dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut juga kemudian akan memberikan dampak terhadap fenomena-fenomena yang akan dihadapi oleh masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha dalam menghadapi beberapa tantangan (Vecchio et al., 2017). Salah satu tantangan yang akan dibahas adalah tantangan para pelaku usaha dalam menghadapi regulasi pajak. Dalam hal ini, para pelaku usaha khususnya yang sudah bertatus PKP harus bersaing dengan keadaan pasar dan harga setelah dikukuhkan sebagai PKP. Untuk tetap menarik konsumen, maka salah satu harapan yang dimiliki oleh para pelaku usaha adalah modal sosial
Modal sosial akan terbentuk jika terdapat jaringan, kepercayaan, norma, dan pemahaman bahasa dan istilah dalam suatu hubungan. Modal sosial dapat dijadikan sebagai strategi bagi para pelaku usaha dalam memanfaatkan hubungan baik sebagai pembentuk sebuah jaringan dalam usaha dengan harapan modal sosial yang tinggi dapat mempertahankan konsumen. Menurut Putnam (2015) Setiap individu dalam kelompok telah memiliki ikatan timbal balik dan kepercayaan.
Menjaga kepercayaan konsumen penting dilakukan oleh para pelaku usaha karena menjadi sebuah fondasi dari hubungan interaksi antara penjual dengan pembeli terutama bagi pengusaha dengan status pengusaha kena pajak atas harga barang yang dijual lebih tinggi dari pada penjual lain dikarenakan penambahan harga yang lebih tinggi dampak dari penambahan tarif PPN terhadap harga jual. Dampak harga yang tinggi tersebut pada akhirnya membentuk norma berperilaku para konsumen karena norma muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan atau dalam istilah lain dikenal juga hubungan simbiosis mutualisme. Dengan demikian, apabila para pelaku yang terlibat dalam suatu hubungan, tidak adanya sikap saling merugikan dan dirugikan maka modal sosial akan timbul dengan sendirinya.
Secara umum kita mengenal modal sosial yang terdapat di Indonesia dapat tercermin dalam hal budaya gotong royong antar masyarakatnya. Tingginya Indeks modal sosial juga semakin terasa dengan tingkat solidaritas masyarakat dilingkungan tersebut. Modal sosial terjadi melalui hubungan sosial antar sesama manusia serta mengarah kepada norma dan jejaring antar manusia di dalam kelompok atau pada lingkungan sekitar tempat kegiatan usaha beroperasi.
”…penting menjaga hubungan sosial karena mereka merupakan pihak paling penting yang membantu kelancaran usaha saya. Dan menurut saya hubungan baik dengan relasi-relasi ini dapat menjadi jembatan rejeki saya dalam jangka panjang. Karena dengan adanya relasi yang baik, maka usaha saya bisa tetap eksis dan bisa membentuk jaringan usaha di masa depan”. (Informan TK1).
”…Begitupun dengan lingkungan sosial yang tidak bisa saya lihat sebelah mata, karena kita adalah makhluk sosial yang pasti akan membutuhkan orang lain juga, jadi selama saya mampu untuk melakukan hal itu, saya akan memberikan sumbangsi terbaik saya untuk lingkungan sosial saya karena disini tempat saya membangun usaha saya, jadi saya juga punya kewajiban untuk tetap membangun lingkungan sosial saya”. (Informan TK2)
”Bagi saya relasi merupakan hal yang paling penting dalam menjaga keberlangsungan usaha saya, baik relasi secara usaha maupun relasi dengan masyarakat sosial sekitar. Dengan menjaga hubungan relasi yang baik, maka dapat memberikan dampak secara jangka panjang bagi usaha saya”. (Informan HM3)
”Saya pun sering ikut aktif dengan kegiatan-kegiatan kampung, bahkan dengan anak-anak muda di kampung. Begitupun misalnya dengan kegiatan-kegiatan bersih-bersih atau dekat-dekat ini kegiatan 17 san, saya ikut memberikan sumbangan dana juga buat meramaikan kegiatan 17 Agustus besok”. (Informan NS5)
Modal sosial berpotensi memberikan keuntungan berhubungan dalam rangka memperoleh potensi hidup yang lebih baik dapat ditopang oleh norma yang baik. Berdasarkan hal tersebut, modal sosial dianggap sebagai sumber daya yang berharga dalam relasi antar manusia, yang bermanfaat bagi mereka untuk mengembangkan diri atau kelompoknya.
Oleh karena itu modal sosial mengacu pada keadaan sosial, nilai, norma serta budaya di masyarakat yang mengatur interaksi antar individu atau lembaga dimana modal sosial tertanam juga termasuknya didalamnya adalah tentang bagaimana kultur, budaya serta pengiplementasian sebuah percayaan. Individu wajib memiliki modal sosial yang baik untuk menjalankan kehidupannya sebagai makhluk sosial. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat harus terakit dengan moral tradisional seperti bertanggung jawab terhadap norma dan pekerjaan bersifat jujur serta dapat memegang komitmen.
Interaksi sosial baik bersifat ekonomi ataupun non-ekonomi ditentukan dengan adanya trust atau kepercayaan dari pihak-pihak yang ada (Baykal & Hesapci, 2022). Kepercayaan sebagai keyakinan bahwa hasil seseorang yang ditujukan dengan tindakan akan sesuai dari sudut pandang. Ada interaksi dua arah antara kepercayaan dan kerjasama. Kepercayaan melumasi kerjasama dan kerjasama itu sendiri akan melahirkan kepercayaan. Pemahaman trust meliputi bagaimana para pelaku usaha membangun kepercayaan dengan konsumen dan identifikasi bentuk kepercayaan yang dibangun.
Kepercayaan akan terbangun jika ada hubungan yang erat antar individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan alasan tertentu misalnya percaya karena sudah kenal lama atau pernah bekerjasama dengan orang yang sama. Kepercayaan bisa luntur apabila ada salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya. Baykal & Hesapci (2022) menggambarkan kepercayaan sebagai kualitas hubungan khusus, yaitu, mitra yang berinteraksi menganggap satu sama lain aspek positif dan motivasi intrinsik untuk mempertahankan hubungan.
Modal Sosial atas Regulasi PPN
Peraturan perpajakan yang mengalami perubahan selalu diikuti dengan berbagai respon termasuk didalamnya adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan fokus pada penelitian ini. Pajak pertambahan nilai menjadi pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dalam peredarannya yang pengenaannya berkaitan dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan produsen.
Dinamika regulasi pajak mengharuskan setiap Wajib Pajak beradaptasi di lingkungan internal dan eksternal, namun dengan peraturan perpajakan yang ada, memungkinkan bagi beberapa wajib pajak untuk melakukan berbagai cara agar tetap diuntungkan. Tindakan tersebut muncul dikarenakan adanya faktor dari stimulus lingkungan, dorongan fisiologis, genetis, pengalaman, dan usia. Faktor-faktor tersebut dapat diukur dan diobservasi dari pelaku usaha itu sendiri. Para informan selalu mencari kepentingannya sendiri, oleh karena itu pajak akan dianggap sebagai biaya yang dapat dihindari, kecuali kemungkinan terdeteksi tinggi dan beratnya denda.
Menurut Permata & Kristanto (2020) bahwa kontrol perilaku berpengaruh terhadap sikap perpajakan. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap pihak berwenang juga berpengaruh terhadap sikap wajib pajak karena unsur modal sosial tidak hanya terbatas pada perilaku individu tetapi juga dapat dipengaruhi dan mempengaruhi oleh pihak yang berkaitan dengan urusan pelaksanaan perpajakan (pertugas pajak) maupun dari rekan sesama profesi di lingkungan sekitar. Apabila didalam lingkungan masyarakat terdapat norma yang saling berbalas, membantu, serta terjalin kerjasama yang baik melalui jaringan sosial masyarakat termasuk dalam keputusan perpajakan.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban yang dimungkinkan untuk dilakukan penghindaran oleh pengusaha kena pajak, karena menilai pengenaan PPN 10% yang tidak berkeadilan dan tidak memihak kepada para PKP, maka hal tersebut mendorong pelaku usaha untuk mencoba mencari celah-celah dalam regulasi PPN yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan memaksimalkan pendapatan dengan tetap mempertimbangankan resiko yang akan terjadi.
”Sejauh ini saya belum ada keinginan mencoba-coba melakukan hal itu, jadi sekalipun mungkin ada peluang besar untuk melakukan itu, untuk saat ini seperti itu pak, ndak tau lagi habis ini jika memang dirasa perlu dilakukan penghindaran pajak oleh perusahaan saya, ya saya melihatlihat terlebih dahulu dampak yang akan ditimbulkan terhadap perilaku ini (Praktik penghindaran pajak)”. (Informan TK2).
“Sejujurnya ada keinginan dari saya untuk kedepan akan mencoba-coba melakukan penghindaran pajak, jadi sebelum itu saya harus lihat-lihat dulu barang kali ada celah yang kemudian nanti dapat saya manfaatkan, tapi pada saat yang bersamaan saya juga ada rasa kekhawatiran juga salah satunya disebabkan adanya sanksi perpajakan yang nantinya malah dapat mempersulit usaha saya. Jadi saya lihat-lihat peluang dulu, dan jika peluang tersebut ada maka waktu itu juga saya mencobanya”. (Informan TK3).
”…beberapa kali telah saya coba praktekan juga, ya pastinya saya melihat-lihat terlebih dahulu dampaknya nanti kepada usaha saya”. (Informan HM4).
“Terutama di usaha toko saya ini saya sangat tidak setuju, apalagi dengan banyaknya macam-macam permasalahan yang saya katakan tadi membuat saya semakin enggan dan banyak cara yang akan dilakukan. toh itu bukan hanya saya sendirian kok yang melakukan ini masih banyak teman-teman sesama pengusaha yang melakukan ini dan banyak yang beralasan ini demi kelangsungan usaha termasuk saya sendiri seperti itu”. (Informan TK1).
Respon tersebut timbul sebagai bentuk tindakan dari perilaku yang ditunjukan dalam merespon rangsangan yang ada. Wajib pajak dalam posisinya sebagai pelaku usaha terhadap adanya PPN dipandang sebagai beban yang mengurangi keuntungan.
Besaran tarif PPN yang ada saat ini para informan menilai tarif tersebut perlu disesuaikan kembali dengan anggapan bahwa tarif yang ada saat ini terlalu memberatkan para pengusa terutama bagi mereka yang telah berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Besaran nilai PPN 10% memaksa informan untuk melakukan pejualan tanpa PPN yang padahal sisi lain daya konsumsi masyarat menurun akibat harga yang terlalu mahal.
Keputusan menaikkan harga akibat dari pengenaan PPN tersebut yang dilakukan oleh informan dikhawatirkan akan mempengaruhi jumlah konsumen akibat kepuasan yang menurun yang menyatakan bahwa harga barang memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan konsumen (Schoeman et al., 2022). Umar et al., (2019) berpendapat bahwa penghindaran pajak termasuk tindakan pengendalian pajak agar terbebas dari konsekuensi kewajiban pajak yang tidak diinginkan. Sedangkan upaya untuk meminimalisir jumlah pajak dibayar, dianggap tidak menyalahi aturan. Sedangkan dengan melakukan tindakan tersebut dapat mempengaruhi dimensi modal sosial yang berdampak kondisi usaha. Ketika perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan akan memperoleh legitimasi oleh masyarakat berupa kerpercayaan pada operasional usaha.
Trust atau kepercayaan menjadi suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung atas tindakan yang dilakukan seperti pelaku usaha yang terpaksa menaikan harga jualnya yang akan menjadi pertimbangan pembeli.
Kepercayaan dalam lingkup jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara anggota masyarakat. Kepercayaan juga memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan perlaku usaha yang turut aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dilingkungan sekitar tempat usaha. Selain itu, Berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kegiatan sosial yang dilakukan informan pada waktu sebelumnya dalam hubungan sosial akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya yang kemudian berdampak pada kelangsungan usaha informan.
Norma Sosial dan Nilai Kepercayan
Norma sosial individu sering kali dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana anggota lain dalam suatu kelompok berpikir dan bertindak, ketika mempertimbangkan pengaruh norma terhadap perilaku, penting untuk membedakan antara norma sosial yang tertanam, diyakini, atau dipercaya oleh seseorang dan norma sosial yang tergambarkan atau yang telah dilakukan oleh banyak orang dan didukung oleh bukti-bukti seperti tindakan-tindakan orang lain yang paling umum dan sesuai untuk suatu situasi.
Jika kebanyakan orang melakukan hal tersebut, maka hal tersebut adalah bijaksana untuk dilakukan juga. Kragh (2016) berpendapat bahwa praduga seperti itu memberikan informasi dan pengambilan keputusan secara cepat untuk seseorang menentukan bagaimana berperilaku pada situasi tertentu. Hanya dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh banyak orang maka seseorang dapat menentukan dengan baik dan efisien untuk dilakukannya sendiri.
Norma sosial injunctive mengacu pada peraturan atau keyakinan tentang perilaku apa yang secara moral diterima dan ditolak. Berbeda dengan norma descriptive yang berdasarkan pada perilaku yang sudah muncul dan telah dilakukan, norma injunctive berdasarkan pada apa yang seharusnya dilakukan (Salmivaara et al., 2021). Artinya norma injunctive lebih berperan melalui peraturan dan sanksi sosial pada umumnya daripada melalui perilaku umum yang muncul. Maksud dari kedua norma diatas cukup serupa antara keduanya karena perilaku yang dapat diterima adalah perilaku yang biasanya dilakukan oleh banyak orang. Termasuk pandangan para informan terhadap penilain perilaku perpajakan pelaku usaha disekitar tempat operasional usaha.
Menjaga hubungan baik dengan semua orang tentu memiliki danpak tersendiri bagi pelakunya, perutama dalam dunia usaha beragamnya faktor kepentingan mendorong para pelaku usaha melakukan banyak hal untuk mencapai tujuan usaha, karena diyakini dapat menjadi sumber keuntungan dan kekuatan daya saing usaha.
”…kami melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar dengan ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan sosial semisalnya ada pembangunan sarana umum kampung di sekitar maka pihak perusahaan kami akan mengambil andil, dan tak jarang kami melakukan kegiatan bersama sebagai bentuk perhatian perusahaan kepada masyarakat”. (Informan HM4).
”…Menjaga hubungan baik itu penting bagi saya pak. Begitulah yang saya rasakan meskipun tidak sebesar yang kita harapkan tapi paling tidak ada keakraban dengan orang disekitar kita, saling membantu satu sama lain. Jadi sangat senang sekali ketika ada kegiatan bersama dengan masyarakat kami bisa melakukan banyak hal ketika kami bekerja dengan gotong royong, dan hal bukan hanya memberikan pengaruh positif untuk kebaikan usaha saja melainkan juga untuk tubuh agar tetap sehat”. (Informan NS5).
Peran penting yang diperoleh dari hasil interakasi yang baik dengan masyarakat dilingkungan sekitar tempat usaha para informan yang memberikan dampak positif bagi berjalannya usaha informan. Karena kelompok dapat menjadi sumber keuangan dan sumber daya manusia untuk berwirausaha dikarenakan adanya hubungan kekerabatan. Dengan adanya interaksi secara berkala dan terciptanya hubungan kekerabatan tersebut dapat menimbulkan kepercayaan dari kelompok. Hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam norma sosial yang dibangun oleh informan dengan masyarakat dilingkungan sekitar tempat usahanya yang menjadikan salah satu modal sosial yang diciptakan informan.
Unsur modal sosial dalam pasar berupa jaringan sosial, kepercayaan, dan norma memiliki peran dalam perdagangan (Putnam, 2015). Partisipasi para pelaku usaha dalam kegiatan sosial memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha. Hubungan kerjasama tersebut merupakan fungsi kelompok yang digunakan untuk mempertahankan usaha yang menunjukan kemampuan masyarakat dalam kelompok untuk bekerjasama membangun jaringan untuk tujuan bersama.
Putnam (2015) menjelaskan modal sosial sebagai jaringan-jaringan, nilai-nilai, norma dan kepercayaan yang timbul diantara para anggota perkumpulan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk manfaat bersama. Dalam penelitian ini, penliti melihat bahwa informan tidak terlepas dari peran orang lain terutama keluarga yang membentuk sebuah ikatan kerjasamayang saling terikat antara satu dengan yang lain dan saling menguntungkan, sehingga pengusahs mampu mempertahankan eksistensinya.
Informan memanfaatkan sumber daya sosial yang terbentuk melalui intraksi sosial dengan relasinya dalam berbagai tindakan sosial baik dengan masyarakat sekitar, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pelanggan. Hubungan ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam kegiatan ekonomi yang telah mereka jalankan, sehingga kedua pihak dapat memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut dapat memenuhi keberlangsungan hidup mereka yang lebih baik bahkan dengan adanya tarif PPN yang menjadikan harga jual yang lebih mahal dari para non-PKP, bahkan fakta lapangan bahwa konsumen terpaksa mengurangi daya konsumsi mereka, artinya konsumen akan menunda pembelian barang, kecuali terpaksa dilakukan pada saat kondisi yang mendesak bagi konsumen.
Bentuk modal sosial para informan pada keberlangsungan usaha berdasarkan adanya unsur jaringan, kepercayaan, norma dan nilai. Dalam penelitian ini hubungan yang terjalin antara informan dengan pelaku usaha lain dalam suatu perkumpulan dilandasi oleh jaringan, kepercayaan, nilai dan norma dari individu yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperluas hubungan sosial. Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pihak-pihak lain dianggap penting termasuk didalamnya adalah nilai kepercayaan dengan anggota keluarga.
Hubungan yang dimiliki informan dengan lingkungan terdekatnya seperti teman atau keluarga sehingga hubungan tersebut bersifat terkuat. Keluarga dimanfaatkan oleh informan sebagai sebuah cara yang diharapkan dapat terus berjalan hingga kegenarasi berikutnya, nilai keyakinan tersebut di gambarkan pada keterlibatan anggota keluarga yang lainnya dalam operasional usaha. Selain diyakini dapat memperkuat kelangsungan usaha juga bertujuan sebagai cara meminimalisir beban perpajakan dengan membagi usaha kepada keluarga yang lainnya namun tetap pada pengontrolan informan.
Norma sosial merepresentasikan sebuah kelompok karena berperan sebagai karakteristik yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sebuah kelompok. Dengan demikian, untuk membentuk norma, harus ada kelompok yang menggambarkan karakteristik norma tersebut. Karakterisitik dari norma itu sendiri dapat menjadi suatu bentuk kekuatan norma sosial dan menjadi unsur pendukung dalam membangkitkan semangat dalam menghadapi regulasi pajak. Kekuatan norma sosial dalam membentuk perilaku terdapat dalam dinamika psikologi sosial yang muncul dalam sebuah kelompok, seperti kecenderungan anggota kelompok untuk melihat satu sama lain untuk mendapat panduan, penegasan, dan persetujuan, dan juga tekanan untuk mencapai keseragaman yang dihasilkan oleh kelompok (Yong et al., 2019). Kelompok yang dimaksud dapat berupa anggota keluarga, komunitas , lingkungan sosial, atau jaringan, dapat berupa kelompok formal atau informal dalam bentuk interaksi secara langsung atau virtual. Unsur paling penting adalah anggota kelompok mempertimbangkan dirinya sebagai teman sebaya yang setara, serupa dalam kepentingan tertentu, dan menganggap pendapat dan perilaku dari anggota kelompok lain relevan dengan dirinya.
Kesimpulan
Secara umum kita mengenal modal sosial yang terdapat di Indonesia dapat tercermin dalam hal budaya gotong royong. Tingginya Indeks modal sosial juga semakin terasa dengan tingkat solidaritas masyarakat dilingkungan tersebut. Modal sosial terjadi melalui hubungan sosial antar sesama manusia serta mengarah kepada norma dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
Modal sosial dapat terbentuk apabila dalam lingkungkan sosial tersebut terdapat kepercayaan terhadap satu sama lain, norma yang disepati bersama menjadi nilai universal, serta adanya jaringan sosial yang terjalin baik dalam lingkup internal maupun dengan ekternal dengan kelompok tertentu. Berbicara tentang modal sosial, tidak hanya akan terbatas pada sesuatu yang bernalai secara material atau financial belaka, lebih dari itu modal sosial dapat memberikan nilai keuntungan sosial yang lebih besar dan berpotensi besar menajaga kelangsungan usaha. Menjaga kepercayaan konsumen penting dilakukan karena menjadi sebuah fondasi hubungan interaksi antara penjual dengan pembeli. Interaksi sosial baik bersifat ekonomi ataupun non-ekonomi ditentukan dengan adanya trust atau kepercayaan dari pihak-pihak yang ada termasuk dalam urusan perpajakan yang menjadi kewajiban pelaku usaha terutama dalam hal PPN bagi para PKP.
Modal sosial yang ditinjau dari norma berperilaku dalam perpajakan bahwa kepercayaan terhadap pihak berwenang juga berpengaruh terhadap sikap wajib pajak karena unsur modal sosial tidak hanya terbatas pada perilaku individu tetapi juga dapat dipengaruhi dan mempengaruhi oleh pihak yang berkaitan dengan cara petugas pajak menunjukan kenerjanya kepada para wajib pajak yang merupakan sebuah norma kewajaran atas kondisi lingkungan sekitar. Hal tersebut turut membentuk nilai kepercayaan para wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, selain itu dari rekan sesama profesi di lingkungan sekitar juga berperan dalam membentuk norma atau kewajaran dalam berperilaku. Sementara itu, bagi PKP regulasi PPN menjadi beban yang dimungkinkan untuk dilakukan penghindaran oleh pengusaha kena pajak, karena menilai pengenaan PPN 10% yang tidak berpihak kepada para PKP yang kemudian mendorong tindakan coba-caba oleh PKP dengan perhitungan resiko yang ada.
Sebagai upaya menjaga kelangsungan usaha pemanfaatan sumber daya sosial yang terbentuk melalui intraksi sosial dengan relasinya dalam berbagai tindakan dan keterlibatan dalam kegiatan sosial lingkungan sekitar untuk memperoleh serta mempertahankan legistimasi berupa hubungan kekerabatan, kepercayaan, nilai dan norma kepada PKP meskipun adanya tarif PPN yang menjadikan harga jual yang lebih mahal dari para non-PKP.
Referensi
Baykal, B., & Hesapci, K. (2022). Recommendation matters: how does your social capital engage you in eWOM? Journal of Consumer Marketing, 9(11). https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JCM-08-2021-4842
Celikay, F. (2020). Dimensions of tax burden: a review on OECD countries. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 25(49), 27–43. https://doi.org/10.1108/JEFAS-12-2018-0138
Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & Desain Riset (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
Kragh, S. U. (2016). Tribe and village in African organizations and business. Personnel Review, 45(1), 51–66. https://doi.org/10.1108/PR-08-2012-0140
Permata, I. D., & Kristanto, A. B. (2020). Pengaruh Modal Sosial Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 5(2), 168. https://doi.org/10.30736/.v5i2.332
Putnam, R. D. (2015). Bowling alone: America’s declining social capital (6th ed., Vol. 21, Issue 1). Routledge. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203
Salmivaara, L., Lombardini, C., & Lankoski, L. (2021). Examining social norms among other motives for sustainable food choice: The promise of descriptive norms. Journal of Cleaner Production, 311, 127508. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127508
Santoso, D., Indarto, I., & Sadewisasi, W. (2019). Pola Peningkatan Kinerja Bisnis Ukm Melalui Modal Sosial Dan Modal Manusia Dengan Kebijakan Pemerintah Sebagai Moderating. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 21(2), 152. https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1764
Schoeman, A. H. A., Evans, C. C., & Du Preez, H. (2022). To register or not to register for value-added tax? How tax rate changes can influence the decisions of small businesses in South Africa. Meditari Accountancy Research, 30(7), 213–236. https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2021-1309
Sinarwati, N. K., Yuliarmi, N. N., & Utama, M. S. (2019). Social Capital And Sustainability of MSMEs. Jurnal UNMUH Jember, 2(2), 53–70.
Umar, M. A., Derashid, C., Ibrahim, I., & Bidin, Z. (2019). Public governance quality and tax compliance behavior in developing countries: The mediating role of socioeconomic conditions. International Journal of Social Economics, 46(3), 338–351. https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2016-0338
Vecchio, P. Del, Minin, A. Di, Petruzzelli, A. M., Pannielo, U., & Pirri, S. (2017). Big data for open innovation in SMEs and large corporations: Trends, opportunities, and challenges. Creativity and Innovation Management, 27(1), 6–22. https://doi.org/10.1111/caim.12224
Yong, S., Sawyer, A. J., & Freudenberg, B. (2019). Tac Compliance in the New Millenium: Understanding the Variables. ResearchGate,Australian Tax Forum, 31, 2.
Zhang, P., & Cain, K. W. (2017). Reassessing the link between risk aversion and entrepreneurial intention: The mediating role of the determinants of planned behavior. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 23(5), 793–811. https://doi.org/10.1108/IJEBR-08-2016-0248
Penulis adalah Anggota IKPI Cabang Surabaya
Danny Wibowo
Email: –
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis
Catatan: Tulisan ini pernah dipublikasikan pada Riset dan Jurnal Akuntansi (SINTA 3) Tahun 2023