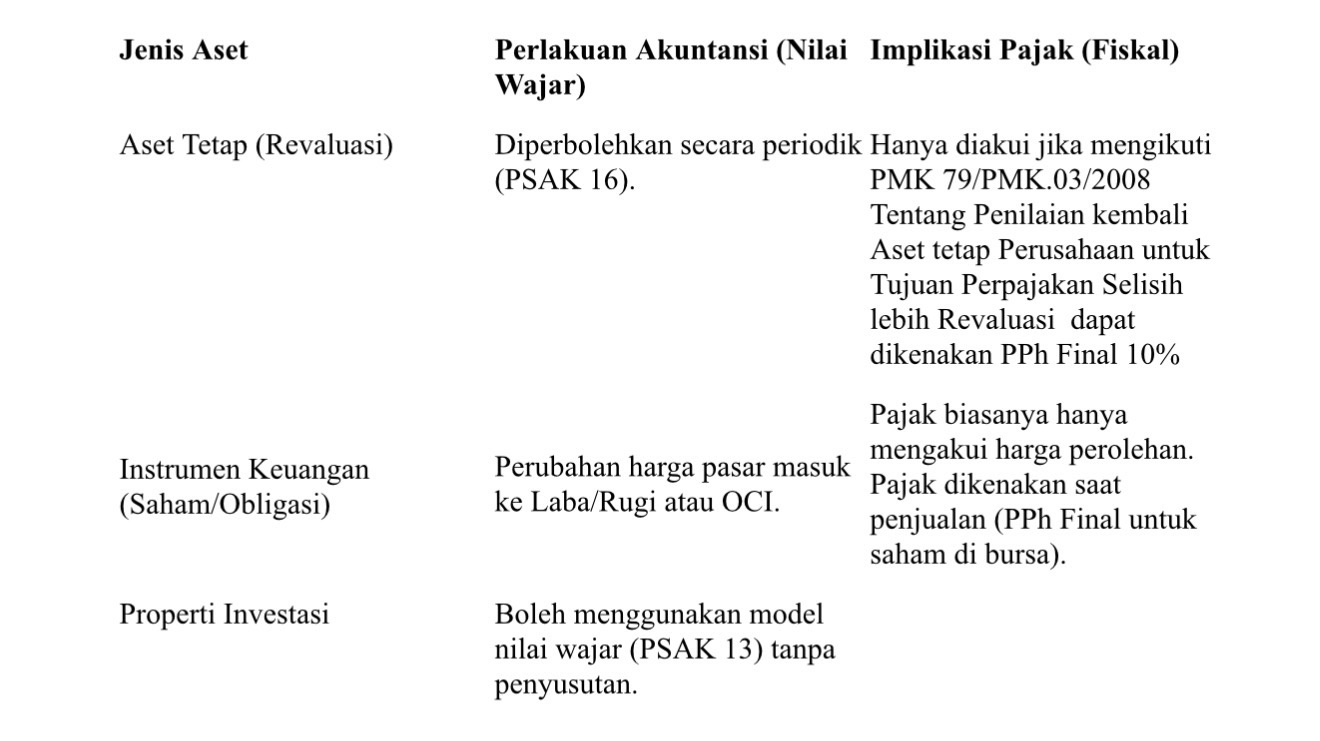Pada hari Rabu, 10 Desember 2025 waktu Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed) kembali memangkas suku bunga acuan (federal funds rate) sebesar 25 basis poin (bps), sehingga suku bunga acuan berada pada rentang 3,5%–3,75%. Keputusan ini menandai fase baru pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat setelah periode pengetatan agresif pada 2022–2023 yang ditujukan untuk meredam lonjakan inflasi pasca pandemi dan guncangan harga komoditas global.
Dalam proyeksi berbagai analis, The Fed diperkirakan masih memiliki ruang untuk kembali memangkas suku bunga secara bertahap pada tahun 2026, dengan kelipatan 25 bps, sepanjang data inflasi dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat bergerak sejalan dengan target dan ekspektasi. Dengan posisi Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar dunia dan dolar AS sebagai mata uang cadangan utama global, setiap perubahan kebijakan suku bunga The Fed tidak hanya berdampak pada perekonomian domestik AS, tetapi juga menimbulkan gelombang (spillover) ke berbagai negara, termasuk Indonesia.
Artikel ini membahas dampak penurunan suku bunga The Fed terhadap perekonomian Indonesia dari empat perspektif utama, yaitu: (1) inflasi, (2) pasar modal, (3) suku bunga acuan Bank Indonesia, dan (4) kinerja perpajakan. Di samping itu, akan diulas secara singkat sejarah peran The Fed dalam membentuk dinamika ekonomi global, sehingga memberikan konteks akademis dan praktis bagi pembaca, baik untuk tujuan publikasi maupun pengajaran.
Sekilas Sejarah The Fed dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Dunia
The Fed dibentuk pada tahun 1913 melalui Federal Reserve Act sebagai respon terhadap serangkaian krisis perbankan yang mengguncang Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tujuan awalnya adalah menciptakan bank sentral yang mampu menyediakan likuiditas darurat (lender of last resort) dan menstabilkan sistem keuangan.
Pada era Depresi Besar (Great Depression) tahun 1930-an, kebijakan moneter The Fed yang cenderung terlambat dan terlalu ketat dinilai oleh banyak ekonom sebagai salah satu faktor yang memperdalam kontraksi ekonomi, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di berbagai belahan dunia. Episode ini menjadi pelajaran penting mengenai peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistemik.
Pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, di bawah kepemimpinan Paul Volcker, The Fed menaikkan suku bunga hingga di atas 15% untuk menghancurkan inflasi tinggi yang mengakar di perekonomian AS. Kebijakan yang kemudian dikenal sebagai Volcker Shock ini berhasil meredam inflasi, tetapi juga mendorong lonjakan biaya pinjaman global dan memicu krisis utang di berbagai negara berkembang, terutama di Amerika Latin.
Pada dekade 1990-an dan awal 2000-an, di bawah Alan Greenspan, The Fed mengelola suku bunga di tengah gelombang globalisasi keuangan dan liberalisasi pasar modal. Beberapa siklus kenaikan dan penurunan suku bunga AS, termasuk periode menjelang krisis finansial Asia 1997–1998, berkontribusi pada dinamika arus modal yang sangat besar ke dan dari negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia, sehingga membuat perekonomian negara-negara tersebut semakin sensitif terhadap kebijakan moneter AS.
Krisis finansial global 2008 menjadi tonggak penting lain. Menyusul kejatuhan Lehman Brothers dan disfungsi pasar keuangan global, The Fed memangkas suku bunga mendekati nol dan meluncurkan program pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE) dalam skala besar. Likuiditas global yang melimpah mengalir ke berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, mendorong penguatan nilai tukar, penurunan yield obligasi, dan kenaikan harga aset finansial.
Pada tahun 2013, ketika The Fed mulai memberi sinyal akan mengurangi skala QE (tapering), pasar global bereaksi keras dalam peristiwa yang dikenal sebagai taper tantrum. Negara-negara emerging markets mengalami arus keluar modal (capital outflows), pelemahan tajam nilai tukar, serta kenaikan yield obligasi. Indonesia merasakan dampak tersebut melalui depresiasi rupiah dan peningkatan biaya pendanaan pemerintah maupun swasta.
Setelah pandemi COVID-19 dan berbagai paket stimulus fiskal-moneter yang sangat besar, The Fed kembali menormalisasi kebijakan dengan menaikkan suku bunga secara agresif pada 2022–2023 untuk meredam inflasi yang melonjak. Siklus pengetatan ini kembali menekan mata uang negara berkembang dan memicu penyesuaian suku bunga domestik di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Dengan konteks historis tersebut, jelas bahwa The Fed bukan sekadar bank sentral nasional, melainkan salah satu aktor kunci yang membentuk lanskap ekonomi dan keuangan global. Setiap perubahan kebijakan suku bunga The Fed berpotensi membawa konsekuensi luas bagi negara-negara lain, baik melalui kanal nilai tukar, arrus modal, harga komoditas, maupun sentimen pasar.
Mekanisme Transmisi Kebijakan The Fed ke Perekonomian Indonesia
Dampak kebijakan The Fed terhadap Indonesia terjadi melalui beberapa jalur utama. Pertama, kanal suku bunga global dan yield spread. Penurunan suku bunga acuan The Fed cenderung menurunkan imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS, sehingga selisih imbal hasil (spread) antara aset berdenominasi rupiah dengan aset berdenominasi dolar AS dapat melebar. Hal ini membuat aset keuangan Indonesia tampak relatif lebih menarik bagi investor global.
Kedua, kanal nilai tukar dan arus modal portofolio. Suku bunga AS yang lebih rendah cenderung menurunkan daya tarik dolar AS sebagai instrumen investasi jangka pendek dan mendorong investor global mencari imbal hasil yang lebih tinggi di negara berkembang. Kondisi ini dapat mendorong arus modal masuk (capital inflows) ke pasar obligasi dan saham Indonesia, yang pada gilirannya mendukung penguatan atau setidaknya stabilitas nilai tukar rupiah.
Ketiga, kanal harga komoditas dan permintaan global. Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, suku bunga yang lebih rendah di Amerika Serikat berpotensi mendukung aktivitas ekonomi global. Bila pertumbuhan global menguat, permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia seperti batubara, CPO, nikel, dan lain-lain dapat meningkat, memberikan dukungan tambahan bagi kinerja ekspor dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Keempat, kanal ekspektasi dan sentimen pasar. Pernyataan resmi The Fed, proyeksi suku bunga (dot plot), dan komunikasi kebijakan lainnya membentuk ekspektasi pelaku pasar global. Jika pasar meyakini bahwa penurunan suku bunga The Fed akan berlanjut, harga aset keuangan global akan menyesuaikan (re-pricing) sejak dini, termasuk di pasar keuangan Indonesia.
Dampak Penurunan Suku Bunga The Fed terhadap Perekonomian Indonesia
Perspektif Inflasi
Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi Indonesia relatif terjaga dalam kisaran sasaran Bank Indonesia. Penurunan suku bunga The Fed berpotensi memberikan dukungan tambahan bagi stabilitas inflasi Indonesia, terutama melalui kanal nilai tukar. Dengan tekanan terhadap dolar AS yang mereda dan kemungkinan menguatnya rupiah, tekanan imported inflation dari barang-barang impor seperti BBM, pangan, dan bahan baku industri dapat berkurang.
Namun demikian, dampak positif tersebut bukan berarti tanpa risiko. Apabila penurunan suku bunga The Fed mendorong pemulihan ekonomi global yang kuat, harga komoditas energi dan pangan dunia bisa mengalami kenaikan, yang kemudian menekan inflasi domestik melalui jalur harga pangan bergejolak (volatile foods) dan harga yang diatur pemerintah (administered prices). Dalam situasi ini, kebijakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi sangat penting untuk mengendalikan ekspektasi inflasi.
Secara keseluruhan, dalam konteks penurunan suku bunga The Fed pada akhir 2025, peluang stabilitas inflasi Indonesia cenderung lebih besar daripada risikonya, selama faktor-faktor domestik seperti pasokan pangan, kebijakan harga energi, dan koordinasi kebijakan fiskal–moneter tetap terjaga dengan baik.
Perspektif Pasar Modal
Penurunan suku bunga The Fed secara historis cenderung bersifat positif bagi pasar keuangan negara berkembang, termasuk pasar modal Indonesia. Dari sisi pasar saham, penurunan suku bunga global menurunkan cost of equity dan meningkatkan valuasi teoritis saham melalui penurunan tingkat diskonto (discount rate). Sektor-sektor yang peka terhadap suku bunga seperti perbankan, properti, dan konsumsi berpotensi memperoleh sentimen positif, terutama jika didukung oleh fundamental domestik yang kuat.
Di pasar obligasi, penurunan suku bunga The Fed dan yield US Treasury akan membuat imbal hasil surat berharga negara (SBN) Indonesia semakin menarik secara relatif. Hal ini dapat mendorong permintaan SBN oleh investor global dan domestik, sehingga menurunkan yield SBN dan pada akhirnya menurunkan biaya pinjaman pemerintah. Penurunan yield SBN juga berpotensi menurunkan biaya pendanaan korporasi melalui pasar obligasi korporasi.
Meski demikian, volatilitas tetap perlu diwaspadai. Perubahan ekspektasi pasar terhadap jalur suku bunga The Fed, data ekonomi AS yang berbeda dari perkiraan, atau eskalasi risiko geopolitik dapat memicu pembalikan arus modal secara cepat. Oleh karena itu, penguatan fundamental domestik, kedalaman pasar keuangan, dan komunikasi kebijakan yang kredibel dari otoritas moneter dan otoritas pasar modal menjadi prasyarat penting untuk mengoptimalkan manfaat penurunan suku bunga The Fed bagi pasar modal Indonesia.
Perspektif Suku Bunga Acuan Bank Indonesia
Penurunan suku bunga The Fed mengurangi tekanan eksternal terhadap perekonomian Indonesia, terutama yang terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah dan arus modal. Dalam kondisi ini, ruang kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) secara selektif dan bertahap menjadi lebih terbuka dibandingkan ketika The Fed berada pada fase pengetatan agresif.
Namun demikian, keputusan Bank Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan The Fed. BI harus mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti proyeksi inflasi domestik, kesenjangan output (output gap), kondisi sektor keuangan, serta risiko eksternal lain yang mungkin timbul dari perlambatan ekonomi global atau dinamika harga komoditas. Dengan kata lain, penurunan suku bunga The Fed memberikan ruang gerak tambahan, tetapi tidak boleh mendorong BI untuk mengambil kebijakan pelonggaran yang berlebihan.
Pendekatan yang paling realistis adalah kebijakan pelonggaran yang hati-hati (cautious easing), di mana BI menurunkan suku bunga secara terbatas dan bertahap, sambil tetap mengandalkan instrumen lain seperti kebijakan makroprudensial, intervensi nilai tukar, dan pengelolaan likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Perspektif Kinerja Perpajakan Indonesia
Kinerja perpajakan Indonesia, yang tercermin dari rasio pajak (tax ratio) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara peers di kawasan maupun negara anggota OECD. Penurunan suku bunga The Fed tidak secara langsung mengubah struktur perpajakan Indonesia, tetapi dapat mempengaruhi basis pajak melalui dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan profitabilitas dunia usaha.
Apabila penurunan suku bunga The Fed berhasil menciptakan lingkungan keuangan global yang lebih kondusif, maka biaya pendanaan investasi dapat menurun dan aktivitas ekonomi domestik berpotensi meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat akan memperluas basis pajak, baik dari sisi Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Orang Pribadi, maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumsi dan investasi.
Di sisi lain, stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi yang terkendali juga membantu dunia usaha dalam melakukan perencanaan keuangan dan investasi, sehingga mengurangi risiko kebangkrutan dan tunggakan pajak. Bagi pemerintah, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong reformasi perpajakan yang berorientasi pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, dan penguatan administrasi perpajakan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dan data yang lebih komprehensif.
Namun, perlu diingat bahwa jika penurunan suku bunga The Fed mencerminkan pelemahan ekonomi global yang lebih dalam, maka kinerja sektor ekspor dan komoditas Indonesia bisa tertekan, yang pada gilirannya melemahkan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Oleh karena itu, strategi perpajakan Indonesia harus adaptif, memanfaatkan peluang ketika siklus global menguntungkan, dan memperkuat basis pajak domestik ketika siklus global berada dalam fase melemah.
Prospek 2026 dan Implikasi Kebijakan
Dengan asumsi The Fed kembali memangkas suku bunga beberapa kali pada tahun 2026, peta kebijakan moneter global akan bergerak menuju rezim suku bunga yang lebih rendah setelah periode “higher for longer”. Bagi Indonesia, skenario ini menghadirkan kombinasi peluang dan tantangan. Di satu sisi, lingkungan suku bunga global yang rendah dapat mendukung pembiayaan pembangunan melalui penurunan biaya pinjaman pemerintah dan swasta, serta mendorong arus modal masuk ke pasar keuangan domestik.
Di sisi lain, ketidakpastian tetap akan membayangi, baik dari sisi geopolitik, dinamika perdagangan internasional, maupun prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. Dalam konteks ini, Indonesia perlu terus memperkuat fondasi domestik, termasuk menjaga disiplin fiskal, stabilitas sistem keuangan, iklim investasi, dan kualitas kelembagaan perpajakan.
Bagi pembuat kebijakan, penting untuk melihat penurunan suku bunga The Fed bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai jendela peluang untuk mempercepat reformasi struktural di dalam negeri. Bagi akademisi dan pendidik, episode ini dapat dijadikan studi kasus aktual tentang interaksi kebijakan moneter global dan perekonomian domestik, serta hubungan antara kebijakan suku bunga, pasar keuangan, dan penerimaan negara.
Ringkasan
Penurunan suku bunga acuan The Fed pada Desember 2025 ke kisaran 3,5%–3,75% merupakan bagian dari siklus pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat setelah fase pengetatan yang cukup agresif. Bagi Indonesia, kebijakan ini memberikan angin segar melalui berkurangnya tekanan eksternal, stabilitas nilai tukar, dan potensi peningkatan aliran modal ke pasar keuangan domestik.
Dari perspektif inflasi, penurunan suku bunga The Fed cenderung mendukung stabilitas harga melalui kanal nilai tukar, meskipun risiko kenaikan harga komoditas global tetap perlu diwaspadai. Dari sisi pasar modal, lingkungan suku bunga global yang lebih rendah berpotensi meningkatkan valuasi aset dan menurunkan biaya pendanaan pemerintah dan sektor swasta. Bagi Bank Indonesia, kebijakan The Fed membuka ruang pelonggaran tambahan, tetapi tetap menuntut kehati-hatian demi menjaga kredibilitas dan stabilitas makroekonomi.
Sementara itu, dari perspektif perpajakan, peluang untuk meningkatkan kinerja penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan pemanfaatan momentum pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan kebijakan yang terukur dan tidak kontraproduktif terhadap iklim usaha. Pada akhirnya, kualitas respons kebijakan domestik—baik di bidang moneter, fiskal, maupun regulasi sektor keuangan—akan menentukan sejauh mana Indonesia dapat mengonversi perubahan kebijakan The Fed menjadi manfaat nyata bagi pembangunan nasional.
Penulis adalah Anggota Departemen Humas PP-IKPI
Donny Danardono
Email: donnydanardono@gmail.com
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis